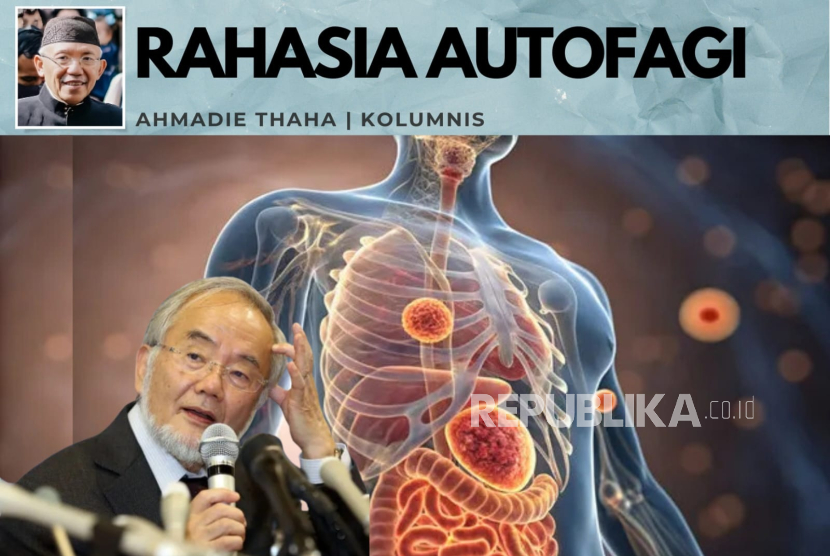Oleh : Zainurrofieq, Anggota Pokja Dakwah Luar Negeri MUI Pusat 2025-2030
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2026 baru berjalan, namun kegelisahan global sudah terasa di banyak penjuru dunia. Ketegangan geopolitik tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan cenderung meningkat. Ironisnya, berbagai persoalan besar yang membayangi dunia sepanjang 2025 pun belum sepenuhnya menemukan jalan keluar.
Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, perang yang terus berlangsung di Eropa Timur, instabilitas di sejumlah negara Afrika, hingga rivalitas terbuka antarnegara adidaya, semuanya menciptakan situasi global yang rapuh dan mudah tersulut.
Sejumlah pakar hubungan internasional, diantaranya Wolfgang Munchau - kolumnis Unherd- memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode paling berbahaya (broader war) dalam satu dekade terakhir, terutama di kawasan Eropa.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, juga menyuarakan keprihatinan serupa, seiring meningkatnya eskalasi konflik global dan melemahnya peran lembaga-lembaga internasional penjaga perdamaian. Kekhawatiran ini turut digaungkan oleh sejumlah politisi dan pemerhati perdamaian di Eropa.
Demikian juga dengan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal yang sama secara tersirat dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) Davos 2026, bahwa Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara dan menolak kekacauan serta konflik. Dalam hal ini, Presiden menyadari bahwa situasi global sedang tidak baik-baik saja, penuh ketidakpastian dan ketegangan.
Dalam situasi seperti ini, dunia seolah kembali berada di persimpangan berbahaya. Ketika diplomasi formal seringkali terjebak pada kepentingan sempit dan logika kekuasaan, muncul kebutuhan mendesak akan pendekatan lain yang lebih bermoral dan berorientasi pada kemanusiaan. Dunia tidak hanya memerlukan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan.
Wasathiyah sebagai Jalan Tengah
Islam sejak awal hadir sebagai agama penengah, bukan agama ekstrem. Prinsip wasathiyah—yang bermakna adil, seimbang, dan moderat—merupakan inti ajaran Islam. Allah SWT berfirman, “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang wasath (tengah), agar kamu menjadi saksi atas manusia.” (QS. Al-Baqarah: 143)
Ayat ini menegaskan peran umat Islam sebagai penjaga keseimbangan dan saksi moral bagi umat manusia. Dalam konteks dunia yang semakin terpolarisasi, peran ini menjadi sangat relevan. Umat Islam tidak dipanggil untuk memperkeruh keadaan, melainkan menghadirkan pandangan yang adil, menenangkan dan solutif.
Wasathiyah bukanlah sikap abu-abu atau kompromi tanpa prinsip. Ia justru menolak dua ekstrem sekaligus: ekstrem kekerasan yang menghalalkan perang atas nama kepentingan politik, serta ekstrem permisif dan apatis yang membiarkan kezaliman demi stabilitas semu. Islam menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila keadilan ditegakkan dan martabat manusia dihormati.
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini mengandung pesan universal bahwa keselamatan manusia merupakan pondasi utama kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga relevan dalam hubungan antarbangsa. Segala bentuk kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri, yang mengorbankan keselamatan manusia bertentangan dengan nilai dasar Islam.
Diplomasi Wasathiyah dan Tanggung Jawab Dunia Islam
Dalam konteks geopolitik global, spirit wasathiyah perlu diterjemahkan ke dalam praktik nyata melalui apa yang dapat disebut sebagai diplomasi wasathiyah. Diplomasi ini bukanlah diplomasi yang naif atau utopis, melainkan diplomasi bermoral yang berpijak pada prinsip kemaslahatan. Dalam kaidah ushul fiqih ditegaskan, “Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih”, mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
Kaidah ini menegaskan bahwa mencegah kehancuran akibat konflik bersenjata harus menjadi prioritas utama. Sejarah menunjukkan bahwa perang hampir selalu melahirkan mafsadat besar: korban sipil yang masif, krisis kemanusiaan, kehancuran ekonomi, serta trauma sosial yang diwariskan lintas generasi. Keuntungan politik yang diklaim sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal moral yang kuat untuk memainkan peran strategis dalam diplomasi wasathiyah. Pengalaman bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman, merawat persatuan, dan menyelesaikan konflik melalui dialog merupakan bukti bahwa pendekatan moderat bukan sekadar wacana. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam berbagai forum nasional dan internasional, secara konsisten mengusung dakwah wasathiyah sebagai jalan tengah yang berkeadaban.
Dakwah wasathiyah tidak cukup berhenti di mimbar atau forum keagamaan. Ia harus menjelma menjadi etika global. Dunia Islam perlu tampil sebagai bridge builder, bukan conflict amplifier. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan diplomasi antarulama, dialog lintas iman, serta kerja sama kemanusiaan lintas negara yang melampaui sekat politik dan ideologi.
Allah SWT mengingatkan, “Dan janganlah kebencian suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus tetap dijaga, bahkan dalam situasi konflik dan kebencian. Inilah fondasi moral diplomasi wasathiyah yang membedakannya dari pendekatan politik kekuasaan semata.
Menurut penulis, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan dunia Islam untuk mendorong perdamaian dunia dan meredam potensi konflik global.
Pertama, menjadi moral broker, bukan power broker. Dunia Islam tidak mengambil posisi sebagai blok kekuatan konfrontatif baru, melainkan kekuatan yang mewarnai dunia dengan otoritas moral dan etika. Dengan mengedepankan narasi keadilan, keselamatan sipil dan martabat manusia. Serta menjadi penengah ketika diplomasi negara mengalami kebuntuan. Peran ini diperkuat dengan peran para ulama, tokoh agama, dialog lintas iman (track two diplomacy) yang mampu menembus batasan politik formal dan meredakan konflik berbasis identitas.
Kedua, kompak mengarusutamakan wasathiyah dalam hubungan antar bangsa dan forum dunia. Salah satu kelemahan dunia Islam adalah fragmentasi sikap. Maka, dunia Islam perlu terus bersuara secara kompak, kolektif dan konsisten dalam isu-isu kemanusiaan dengan berfokus pada perlindungan sipil dan pencegahan kerusakan akibat konflik. Sehingga, wasathiyah tidak hanya menjadi wacana keagamaan an sich, tetapi menjadi prinsip praktis dalam meredam eskalasi dan menjalin persaudaran.
Ketiga, menghadirkan keteladanan, lebih dari retorika. Penyelesaian konflik secara damai di dalam negeri dunia Islam sendiri akan memberikan keteladanan bagi lingkungan global. Perlindungan kaum minoritas, serta tata kelola yang adil dan inklusif akan memberikan inspirasi konkrit tentang komitmen perdamaian. Ketika dunia Islam mampu menjaga stabillitas dirinya sendiri maka pengaruhnya akan lebih kuat, lebih didengar dan lebih meyakinkan untuk membawa dunia kepada perdamaian.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh ancaman perang, dunia Islam dipanggil untuk menghadirkan suara nurani. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan keteladanan; bukan dengan paksaan, tetapi dengan keadilan. Jika spirit wasathiyah ini mampu dikonsolidasikan, dunia Islam dapat berkontribusi nyata dalam menjahit kembali serpihan perdamaian global yang kian rapuh.
Inilah amanah keumatan dan tanggung jawab peradaban yang tidak boleh diabaikan.

 2 hours ago
3
2 hours ago
3