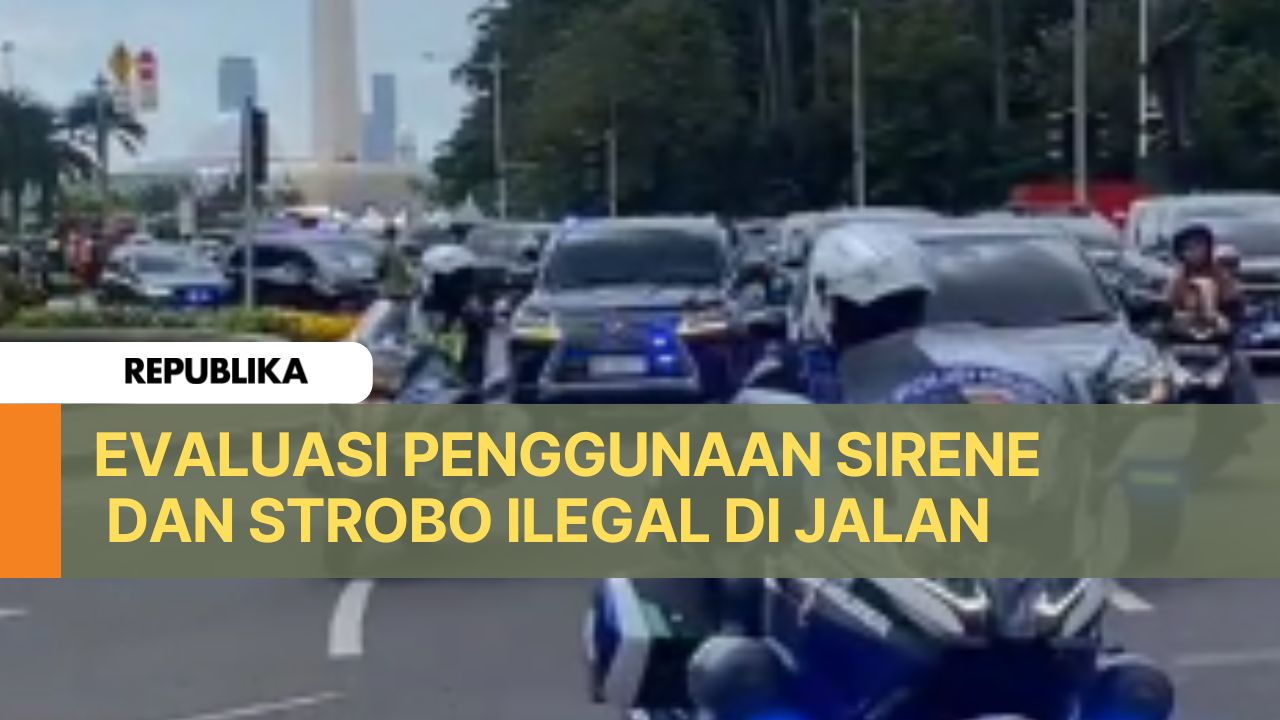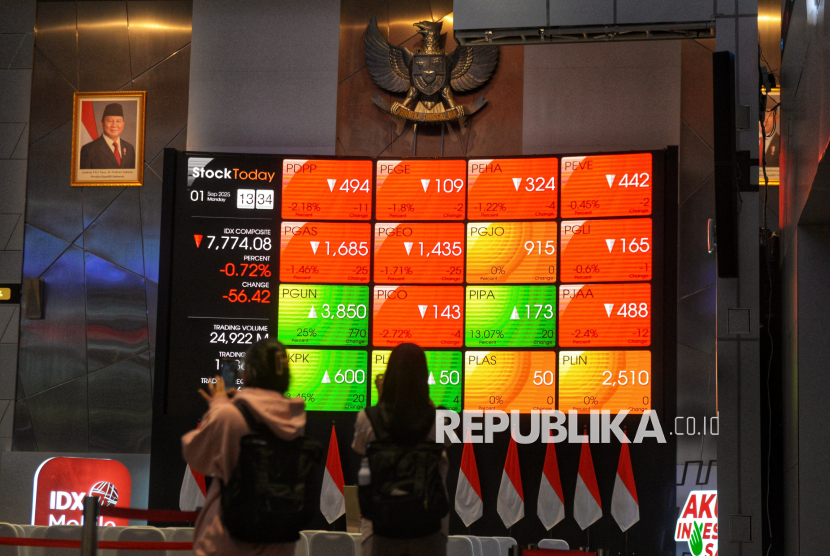Oleh : Badri Munir Sukoco, Guru Besar Manajemen Strategi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bulan lalu, dunia pendidikan tinggi mendapatkan berita bahagia dan berita duka. Berita bahagianya ketika perguruan tinggi (PT) Indonesia masuk dalam Top 100 dunia pada Times Higher Education (THE) IMPACT, yakni UNAIR (#9), UI (#30), dan UGM (#82). PT elit Indonesia lainnya juga memiliki peringkat yang membanggakan.
Sehari setelahnya, lima PT Indonesia naik peringkatnya dalam Quacquarelli Symond (QS) World University Ranking (WUR) 2026. UI pertama kalinya masuk dalam jajaran Top 200 dunia (#189), diikuti UGM (#224), ITB (#255), UNAIR (#287), dan IPB (#399). Kebijakan pemerintah dalam 10 tahun terakhir untuk mendorong PT berkelas dunia mulai menunjukkan hasilnya.
Hampir bersamaan, laporan terbaru Research Integrity Risk Index (RI2) menempatkan PT kita dalam daftar yang dipertanyakan integritasnya. Sebagai fakta, bagaimana kita memulihkan kepercayaan publik pada riset dan PT Indonesia?
Integritas Riset
Didefinisikan sebagai semua faktor yang mendukung praktek riset yang baik, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam proses penelitian. United Kingdom Research Integrity Office (UK-RIO) mengoperasionalkannya melalui 5 kriteria: kejujuran, transparansi, akuntabilitas, terhormat, dan sesuai prosedur (rigour). Dalam konteks ini, kepercayaan dan keyakinan publik akan hasil riset akan terjaga bila kelimanya dilakukan.
Publikasi pada jurnal ilmiah dimulai dengan evaluasi editor sebelum dikirimkan pada minimal 2 reviewer yang tidak diketahui oleh penulis, namun kredibilitas ilmiahnya tinggi, dikenal dengan proses double blind review. Editor akan mengundang reviewer yang ahli dalam topik yang diangkat, dari beragam penjuru dunia. Kelima kriteria dari integritas riset tersebut dievaluasi oleh reviewer. Hasil review disampaikan kepada peneliti, dan bila minor atau major revision, wajib merevisi sesuai masukan dan pertanyaan yang diajukan reviewer. Siklus ini, biasa disebut ronde, berkisar antara 3-6 bulan. Proses review and revise (R&R) ini bisa terjadi dalam 1 hingga 4 ronde, 1 hingga 3 tahun, tergantung kualitas jurnal, reviewer, dan memuaskannya jawaban dari peneliti.
Proses yang panjang inilah yang dimanfaatkan oleh pengelola predatory journals (PJ) atau predatory publishers (PP) untuk menyingkat proses R&R. Istilah PJ dan PP dipopulerkan oleh Jeffrey Beall sejak 2008 lalu, menyikapi maraknya proses publikasi ilmiah bermotif uang dengan integritas riset rendah. Pada saat yang sama, terdapat permintaan cukup besar untuk publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan di program pascasarjana (magister dan doktor), khususnya di negara-negara berkembang yang belum memiliki budaya ilmiah yang kuat. Tanpa proses R&R yang layak, sepanjang membayar article processing charge (APC), hasil riset tersebut dipublikasikan. Bahkan ada yang dalam hitungan jam. Banyak hasil riset yang tidak terverifikasi integritasnya terpublikasi pada jurnal ilmiah, bercampur dengan hasil riset yang terpublikasikan menggunakan proses R&R yang ketat. Secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang karena bercampurnya publikasi tanpa saringan integritas yang ketat.
Indeks Resiko Integritas Riset
Melengkapi Beall’s list, Prof. Lokman I Meho dari American University of Beirut mengembangkan Research Integrity Risk Index (RI2). Terdapat dua komponen yang digunakan: retraction risk dan delisted journal risk. Retraction risk mengukur sejauh mana hasil riset yang dipublikasikan sebuah PT ditarik karena terindikasi fabrikasi (pemalsuan) data, plagiarisme, pelanggaran etika, memanipulasi proses review atau kepenulisan, maupun metodologi riset yang salah. Delisted journal risk mengukur seberapa banyak publikasi yang dihasilkan PT tertentu pada jurnal-jurnal yang dikeluarkan dari database Scopus atau Web of Science dikarenakan pelanggaran standar publikasi, editorial, maupun proses review. Mengingat data-data yang digunakan berasal dari database yang bisa diakses publik, tentunya validitas RI2 tidak diragukan.
Secara umum, PT Singapura memiliki skor RI2 terendah di ASEAN, termasuk University of Philippines. PT yang memiliki skor >0,252 (red flag) terdapat 6 PT dari Malaysia, 5 PT dari Indonesia, Malaysia 6 PT, dan 1 PT dari Vietnam. Untuk yang beresiko tinggi, Malaysia juga diwakili 6 PT, 3 PT dari Indonesia, dan Vietnam serta Thailand masing-masing 2 PT.
Memulihkan Kepercayaan
Dalam konteks riset, publik percaya bahwa PT senantiasa berusaha melakukan riset dan melaporkan hasilnya dengan integritas tinggi untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Ketidakpercayaan muncul bilamana ekspektasi positif tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Mengacu pada crisis life cycle theory (Fink, 1986), terdapat empat tahapan ketidakpercayaan publik. Dimulai oleh Prodromal, ketika peristiwa pelanggaran terjadi dan terakumulasi. Indikasi predatory journals secara global telah diwaspadai sejak Jeffrey Beall dari University of Colorado mempublikasikan daftar PJ dan PP sejak 2011. Di Indonesia, isu tersebut sudah mendapatkan perhatian para peneliti dan dosen pada periode 2014-2016. Mengingat konsekuensi dan sanksi secara institusional, baik akademik dan non-akademik, belum jelas; menjadikan publikasi pada PJ dan/atau PP fenomena gunung es pada PT Indonesia. Berikutnya tahapan Akut, ketika perhatian semakin luas dan terjadi dalam waktu yang singkat.
Kajian RI2 yang dilakukan oleh Prof Meho mendapatkan banyak perhatian publik, apalagi ketika lima PT elit Indonesia masuk dalam kategori red flag. Tahapan ini sangat krusial, sebelum menjadi tahapan Kronis yang membutuhkan pendekatan efektif agar dampak dari krisis kepercayaan publik pada integritas riset PT mulai melemah, meskipun memerlukan waktu yang panjang. Terakhir, tahapan Terminasi dengan berangsur hilangnya dampak dari krisis kepercayaan publik yang terjadi.
Dalam konteks ini, terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan oleh pimpinan PT untuk memulihkan kepercayaan publik, sebagaimana yang disarankan oleh Bachmann dkk. (2015): transparansi dan regulasi. Transparansi akan apa, kenapa, dan bagaimana hal tersebut terjadi perlu disampaikan kepada publik. Hal ini penting sebagai dasar membangun kembali kepercayaan publik, bahwa PT mengakui dan menyadari memang terdapat sivitas akademika yang menjadi korban bahkan penerima manfaat dari PJ dan/atau PP. Regulasi menunjukkan tindak lanjut yang akan dilakukan, baik oleh PT maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk meminimalisir dan menghilangkan peluang terjadinya publikasi karya ilmiah yang dipertanyakan integritasnya.
Regulasi bisa ditujukan bagi dosen atau peneliti yang dikaitkan dengan sistem promosi, insentif kinerja, hak untuk membimbing mahasiswa Magister dan/atau Doktor maupun dana riset yang boleh diajukan. Adapun bagi mahasiswa, sanksi terberat
hingga pencabutan gelar yang diberikan bisa diperkenalkan agar semua pihak menjunjung tinggi integritas riset. Bagi institusi (PT), beragam skema pendanaan maupun peraturan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bagian regulasi. Tentu sanksi sosial bisa menjadi salah satu mekanisme untuk meminimalisir pelanggaran integritas di masa depan. Capacity building, terutama melalui workshop dan upgrading para peneliti dan mahasiswa untuk mampu menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal yang bereputasi dan bermartabat wajib dilakukan.
Rekomendasi
Krisis kepercayaan publik pada PT Indonesia menjadi keprihatinan bersama. Dibutuhkan upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif; agar kepercayaan publik pada PT dan sivitas akademika segera pulih. Transparansi dan regulasi sangat perlu dilakukan agar kemanfaatan dari riset yang dilakukan, khususnya sains dan teknologi, meningkat karena dipercaya oleh masyarakat.
Sejalan dengan penekanan pentingnya sains dan teknologi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Hal ini tercipta melalui riset yang berintegritas tinggi dan bermanfaat berupa teknologi atau kebijakan yang menjadikan semua lini kehidupan bangsa menjadi lebih efektif, efisien, dan berdaya saing. Daya saing yang mampu meningkatkan kapabilitas inovasi bangsa mewujudkan Indonesia Maju 2045.

 1 month ago
20
1 month ago
20