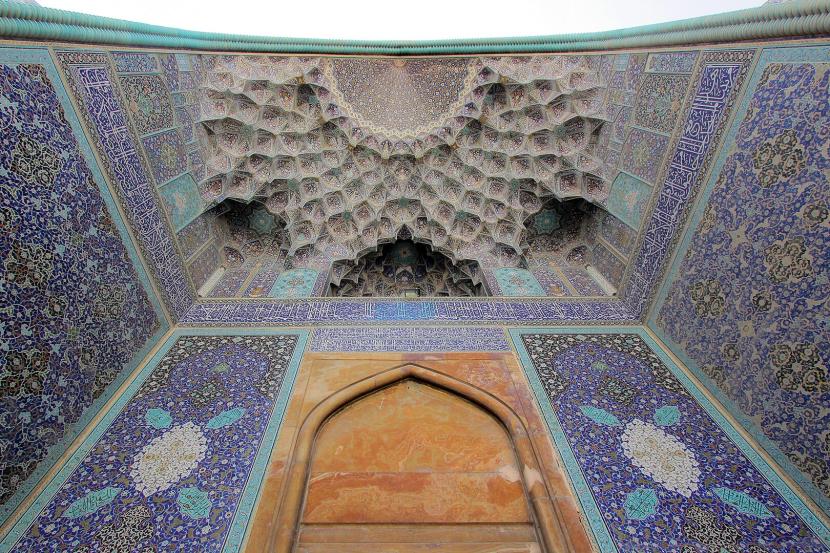REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Noor Huda Ismail
Dunia memang belum juga lepas dari luka. Bumi hangus di Gaza, kelaparan di Yaman, konflik berdarah di Sudan, serangan atas Iran dan Lebanon, Israel yang terus bertindak dengan semena-mena. Sementara itu, Islam banyak disebut dengan nada ketakutan di Eropa dan dunia Barat lainnya.
Globalisasi yang katanya menyatukan justru memicu akselerasi penyebaran konflik. Ketidakadilan serta diskriminasi menjelma sebagai notifikasi di layar ponsel: terus bermunculan tanpa bisa diabaikan, tak jarang membuat emosi meledak.
Namun hampir tak terdengar berita tentang eksodus angkat senjata besar-besaran seperti masa lalu semisal ke Afghanistan, Mindanao Filipina, atau juga Suriah. Narasi perlawanan sepertinya memang telah bermetamorfosis — dari mimbar ke layar, dari senapan ke smartphone.
Sacred Values, Nilai-Nilai Sakral yang Tak Bisa Ditawar
Adalah antropolog Amerika, Scott Atran, yang pertama kali memunculkan konsep sacred values — nilai-nilai sakral yang menggerakkan perilaku individu maupun kelompok, nilai-nilai yang tak bisa ditawar, bahkan oleh logika atau iming-iming duniawi.
Dalam konteks gerakan jihad seperti Jamaah Islamiyah (JI), misalnya, nilai sakral itu bukan sekadar terkait cita-cita khilafah, tetapi juga semangat melawan kedzaliman, dan semangat berdakwah. Nilai sakral itulah yang membuat para jihadis itu tetap teguh, meski dihantam peluru atau diserbu narasi tandingan. Apa pun risikonya, apa pun konsekuensi atau balasannya, nilai-nilai sakral itulah kebenaran yang harus dijalankan.
Sacred values itu seperti api unggun kecil yang bisa menghangatkan, namun bisa pula membakar — bergantung siapa yang mengelola. Maka ketika JI membubarkan diri pada Juni 2024 lalu, bukan berarti mereka kehilangan bara. Barangkali hari ini mereka ingin menjadikan nilai-nilai sakral mereka sebagai lentera — cahaya yang tidak membakar, tetapi menerangi.
Dari Dapur Kaderisasi ke Dapur Tafsir Ulang
Sejak masa awal pendiriannya, JI menjadikan pesantren-pesantren seperti Darusy Syahadah sebagai dapur kaderisasi. Kekuatan utama mereka bukan hanya pada doktrin ideologis, melainkan pada keberhasilan menciptakan atmosfer epistemik yang mencekik: satu kebenaran mutlak, satu otoritas tunggal, dan satu cara menjadi Muslim yang baik — yakni dengan menjadi bagian dari JI.
Dalam dunia sempit seperti itu, berpikir kritis dianggap membangkang, perbedaan menjadi ancaman, dan kritik disamakan dengan kekufuran. Professor hukum Islam di UCLA, Khaled Abou El Fadl, menyebutnya dengan istilah “The Great Theft” (2005): pencurian Islam dari tangan para pemikirnya, yang dikurung dalam penjara literalisme dan hasrat kekuasaan. Islam yang selama berabad-abad tumbuh dalam perdebatan mazhab dan ijtihad, dikerdilkan jadi agama serba-haram dan serba-takfiri.
Akan tetapi zaman berubah, dan di pesantren-pesantren itu, tafsir agama mulai direvisi. Dalam pernyataan pembubarannya, JI mengungkapkan alasan tentang hasil kajian mendalam atas arah perjuangan organisasi selama ini yang dianggap keliru.
Selaras dengan pernyataan pendiri Darusy Syahadah dan mantan ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan veteran Afghanistan, Mustaqim, dalam sebuah wawancara "Kalau JI tidak mau bubar, minimal harus berubah." Pernyataan yang dimaksudkan bukan sebagai ultimatum, tetapi sebuah ajakan. Bak santri yang berkata kepada gurunya, "Yai, boleh saya bertanya?" — penuh hormat namun bernada kritis.
Dan Abu Rusydan, yang dijuluki "penjaga rumah JI," akhirnya membuka pintu perubahan itu. Veteran Afghanistan era 1980-an ini sadar bahwa organisasi hanyalah wasilah atau sarana, bukan tujuan akhir. Kalau sudah tidak lagi membawa maslahat kebaikan ya bisa dilepas — seperti peci yang dulu pas, tetapi sekarang terlalu sempit dan menyebabkan pusing.
Dari Takfiri ke Tafsir Baru
Dasar intelektual pembubaran JI terangkum antara lain dalam buku Attatharruf karya Para Wijayanto, veteran Moro, yang senyatanya bukan sebuah karya individu karena lahir dari gotong-royong para ustaz pesantren. Mereka membaca ulang Ibnu Taimiyah, menyandingkannya dengan literatur Barat.
Ironis? Mungkin. Tapi justru di situlah dinamika transformasinya. Setelah dulu alergi Barat, kini mengutip pemikiran mereka demi membongkar cara berpikir lama yang dianggap keliru dan usang.
Dan ternyata JI bukan satu-satunya yang berbelok. Di Tunisia, Ennahda meninggalkan ambisi revolusi dan memilih jalur sipil. Di Marawi, Filipina, para mantan simpatisan Abu Sayyaf dan ISIS kini terlibat dalam perundingan damai. Di Pakistan, madrasah konservatif mulai bicara soal hak asasi manusia.
Indonesia Sebagai Lokomotif Perubahan
Selama sepuluh tahun dari empat belas tahun jangka waktu yang menjadi fokus pengamatan Global Terrorism Index, Indonesia masuk di posisi 30 teratas negara yang paling dibebani terorisme. Karenanya pembubaran diri JI, yang semula dikenal sebagai salah satu kelompok paling radikal di Indonesia, menjadi tonggak tersendiri bagi sejarah perjuangan negara ini menghadapi ancaman teror dan kekerasan.
Tonggak pencapaian tersebut tentu merupakan hasil berbagai pihak. Selain pendalaman dan kemudian pembaruan tafsir agama oleh kelompok-kelompok seperti JI, sebagaimana telah disebutkan, pemerintah dan masyarakat luas — terutama melalui berbagai organisasi sipil — juga tak sedikit memberikan kontribusi.
Pihak Pemerintah Indonesia, misalnya, bukan hanya mengandalkan pendekatan frontal menggunakan kekuatan fisik dan aksi militer, namun juga pendekatan-pendekatan persuasif serta dialog. Dan tandem kedua pendekatan tersebut nyata-nyata telah membuahkan hasil.
Selain itu, banyak organisasi sipil yang peduli dengan pencegahan radikalisme serta reintegrasi mantan pelaku terorisme. Mereka menjadi partner pemerintah dengan melakukan pendampingan dan menggencarkan narasi tandingan — kampanye dan edukasi untuk membendung upaya penyusupan paham radikal, terutama yang menyasar kalangan muda melalui media sosial dan saluran-saluran online.
Tidak sia-sia, sejumlah peneliti dari Soufan Center (2025) — lembaga riset keamanan global — bahkan menyebut Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, layak menjadi contoh bagi kawasan lain dalam penanganan terorisme. Indonesia punya peluang jadi lokomotif perubahan, meski harus tetap waspada dan tidak malah mabuk kemenangan.
Sebuah Awal, Bukan Akhir
Apakah berarti ekstremisme sudah tamat? Andai semudah itu.
Sacred values yang sama bisa berganti wujud — dari baju koko ke hoodie, dari majelis taklim ke grup Telegram, dari baiat fisik ke “like” dan “share.” Dunia digital adalah arena jihad baru: tanpa medan perang, tapi penuh algoritma dan jebakan filter bubble.
Kasus remaja di Malang dan Bali yang teradikalisasi secara daring menjadi contoh nyata bahwa medan perang sudah berubah. Jika Palestina terus dibombardir, jika umat Islam terus dijadikan bulan-bulanan kampanye sayap kanan, maka bahan bakar kemarahan itu akan selalu tersedia.
JI boleh bubar, tetapi semangat perlawanan tidak serta-merta padam. Kalau tidak diberi ruang damai untuk mengekspresikan sacred values, nilai-nilai itu bisa menemukan jalan sendiri — yang bahkan bisa jauh lebih gelap.
Bagaimanapun harapan tak boleh padam. Pesantren yang dulu dicurigai sebagai inkubator ekstremisme, kini sangat mungkin menjadi inkubator transformasi. Mereka tidak hanya mencetak penghafal Alquran, tapi juga penghafal sejarah — dan pengubah arah.
Kini dari ruang ngaji yang sama, lahir diskusi baru. Santri yang dulu diam-diam dikirim ke Suriah, sekarang menjadi pencerita yang memaparkan perbedaan Islam dari Islamisme. Yang dulu mengutip hadis untuk perang, kini mengutipnya untuk aksi kemanusiaan. Dari jihad bersenjata ke jihad lingkungan — melawan sampah dan pemanasan global.
Mari rayakan potensi transformasi ini dengan hati-hati. Tidak perlu berlebihan, sebaliknya juga tidak perlu sinis. Seperti membesarkan anak remaja yang baru tobat: beri ruang, beri dukungan, tapi tetap pasang CCTV.
Kalau ada satu pelajaran besar dari kisah ini, maka ia adalah: jangan pernah remehkan kekuatan ruang ngaji. Di sanalah ideologi bisa diperhalus, bahkan dibongkar — oleh murid yang tahu cara bertanya, dan guru yang bersedia mendengar.
JI boleh bubar. Tapi dunia masih panas. Dan di tengah semua itu, kita masih punya harapan: bahwa perubahan, betapapun lambat, tetap dapat diupayakan — selama masih ada yang mau membuka kitab sambil menyeduh kopi dan berkata, "Mari kita baca ulang semuanya."

 3 months ago
44
3 months ago
44