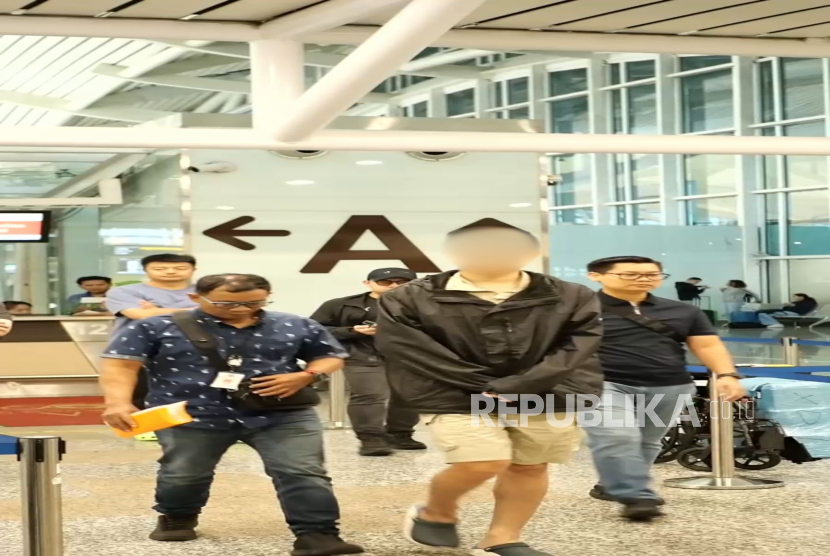Gili Argenti
Gili Argenti
Sejarah | 2025-05-01 18:00:45
 Aksi unjuk rasa aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
Aksi unjuk rasa aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
Di dalam studi gerakan sosial di Indonesia gerakan mahasiswa senantiasa memberikan kontribusi sangat besar bagi arah perjalanan politik dan demokrasi di negeri ini, kiprah mereka digambarkan seperti istilah “patah tubuh hilang berganti”, artinya pada setiap zaman yang senantiasa berubah dan berganti, kelompok mahasiswa senantiasa mengambil peran pentingnya sebagai pelopor perubahan (Culla, 1999).
Bentang sejarah politik Indonesia mencatat peran mahasiswa berawal dari tahun 1920-an, mereka membentuk berbagai organisasi pergerakan kebangsaan menyuarakan persatuan lintas suku, agama, dan ideologi untuk melawan kolonialisme Belanda. Kemudian pada tahun 1940-an kelompok mahasiswa ini terlibat aktif di dalam revolusi kemerdekaan, mereka ikut mengangkat senjata dan bergerilya masuk ke hutan-hutan mengusir kaum penjajah, yang hendak kembali menjajah Indonesia pasca dibacakan teks Proklamasi 1945.
Sedangkan tahun 1960-an kelompok mahasiswa terlibat di dalam pergerakan menggulingkan pemerintahan Orde Lama. Setelah Presiden Soekarno berhasil dijatuhkan dari kursi kekuasaan, kemudian rezim berganti ke pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kelompok mahasiswa tetap menjaga stamina gerakan menjadi kelompok oposisi konstruktif mengkritisi penyelewengan kekuasaan Orde Baru, pada masa ini kita mengenal gerakan mahasiswa angkatan 1970-an (Malari, Ikrar Mahasiswa Indonesia, dan Era NKK/BKK), angkatan 1980-an (kelompok studi dan komite aksi), dan 1990-an (gerakan reformasi).
Gerakan Moral
Keterlibatan mahasiswa di dalam gerakan sosial dari masa ke masa itu, masih dalam kerangka gerakan moral. Gerakan mahasiswa meski kerap bersinggungan dengan kekuasaan politik, sejatinya bukanlah gerakan politik praktis. Menurut Soe Hok Gie, intelektual Indonesia alumni Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI), menjelaskan gerakan mahasiswa itu berada dalam koridor sebagai gerakan moral, tidak memiliki tujuan politik praktis, seperti merebut kursi kekuasaan politik untuk menjadi penguasa baru, menggantikan rezim telah mereka runtuhkan (Maxwell, 2001).
Sedangkan di dalam istilah Arief Budiman, gerakan mahasiswa itu seperti seorang resi (begawan, guru, petapa) yang tinggal di padepokan untuk mengabdikan diri pada kebenaran, serta memiliki kemampuan membaca tanda-tanda zaman, sehingga dapat mengetahui kebobrokan di dalam tubuh pemerintahan, peran resi sangat penting memberikan peringatan kepada penguasa. Resi tidak memiliki kepentingan pribadi untuk meraih kekuasaan dan kedudukan, kritik yang mereka sampaikan murni mewakili kegelisahan di tengah-tengah masyarakat (Budiman, 2000).
Gerakan mahasiswa harus memiliki komitmen terhadap kondisi masyarakat, dengan memberikan respon kritis pada pengelolaan jalannya kekuasaan. Gerakan moral memiliki makna melakukan koreksi terhadap praktik pengelolaan kekuasaan yang terbukti melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gerakan moral berpretensi bukan pada kalah dan menang, maupun kuat dan lemah, tetapi tidak melibatkan diri dalam perebutan jabatan-jabatan politik pemerintahan, harus steril dari keinginan berpolitik praktis.
Artinya gerakan mahasiswa itu merupakan kekuatan civil society yang menjaga jarak dengan entitas politik praktis, alasannya agar mahasiswa bisa independen serta lebih jernih melihat berbagai persoalan bangsa, tidak dibayang-banyangi kekuataan patron tertentu. Tugas gerakan mahasiswa dianggap selesai ketika berhasil memperjuangkan tuntutannya, mereka kembali ke kampus menyelesaikan masa studinya, sambil mengawasi jalannya pemerintahan dari luar sistem politik.
Gerakan mahasiswa tahun 1998 memiliki posisi penting di dalam sejarah politik Indonesia, kesuksesan angkatan ini melakukan transformasi sistem politik dari otoriter-totaliter ke sistem politik demokrasi, memiliki jejak kesamaan dengan senior mereka, yaitu angkatan 1966, yang berhasil menggusur pemerintahan Orde Lama, perbedaannya angkatan 1998 berkonfrontasi langsung dengan pihak militer yang menjadi penjaga status quo, sedangkan angkatan 1966 justru sebaliknya mereka menjalin aliansi strategis dengan militer untuk menjatuhkan Presiden Soekarno.
Sejarah KAMMI
Salah satu organisasi pergerakan mahasiswa angkatan 1998 adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), organisasi kemahasiswaan ekstra kampus ini didirikan pada 29 Maret 1998, pada acara Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Seluruh Indonesia (FS-LDK) Ke X diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) di seluruh Indonesia ketika itu.
Kemunculan KAMMI di dalam dunia pergerakan mahasiswa, bagi kalangan yang belum memahami aktivitas dakwah kampus bisa jadi mengejutkan, disebabkan sebelum terbentuknya KAMMI, para aktifis LDK di dalam kegiatan sehari-hari yang tampak di kampus, terkesan sangat jauh dari kegiatan berbau politik, komunitas dakwah kampus ini di kenal menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bersifat keagamaan, seperti aktivitas mentoring keislaman, kegiatan ramadan di kampus, atau kegiatan lain bernuansa spiritual, terdapat stigma bahwa kelompok LDK menjauhi hingar bingar wacana, perdebatan, dan isu politik.
Pendapat ini tentu saja keliru, karena selama kegiatan mentoring keislaman sebenarnya terjadi internalisasi nilai-nilai politik kepada mahasiswa, misalnya ketika pemilu di masa Orde Baru yang penuh kecurangan, rekayasa, dan mobilisasi. Kalangan aktivis dakwah kampus secara diam-diam memilih aksi tidak memilih atau golput, kesepakatan terorganisir antar LDK itu terjadi secara diam-diam atau tidak terpublikasi ke publik di Pemilu 1992 dan 1997, dengan menggunakan justifikasi doktrin “Al-Wala” dan “Al-Bara”, dua istilah sangat familiar di kalangan aktifis pergerakan Islam (Rahmat & Najib, 2001). Al-Wala berarti loyalitas, kecintaan, dan dukungan kepada kebenaran, terutama kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, sedangkan Al-Bara berarti berlepas diri, menjauhkan diri dari sesuatu yang merusak keimanan (Huda, 2021).
Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru berkuasa dinilai para aktivis dakwah kampus itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi di dalam pemilu menjadi suatu keniscayaan, untuk menunjukkan posisi politik akitivis dakwah kampus dengan pemerintahan Presiden Soeharto.
Kehadiran Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di dunia kemahasiswaan tidak bisa dilepaskan dari peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, didirikan oleh M. Natsir salah seorang politisi senior Partai Islam Masyumi, pendirian DDII merupakan ijtihad politik dilakukan M. Natsir dan kawan-kawan pasca kegagalan merehabilitasi kembali Partai Islam Masyumi pada awal Orde Baru, pemerintah tidak merestui kembalinya partai Islam terbesar di Indonesia ini ke panggung politik nasional. Kemudian M. Natsir memilih mendirikan lembaga pendidikan dan dakwah sebagai wadah baru bagi kelompok eks-Masyumi, tetap berkiprah di tengah-tengah masyarakat.
DDII berperan besar melahirkan generasi baru Islam melalui LDK, berawal dari pemberian beasiswa kepada anak-anak muda Indonesia untuk melanjutkan studi ke berbagai negara di Timur Tengah, pemberian beasiswa ini melalui kerja sama DDII dengan berbagai organisasi Islam internasional (Damanik, 2002). Selama studi ke luar negeri anak-anak muda Islam ini bersentuhan dengan berbagai pemikiran Islam, serta mengenal berbagai organisasi pergerakan Islam, salah satunya Ikhwanul Muslimin (Mesir), sepulang studi dari Timur Tengah, mereka kemudian mentransmisikan pemikiran Islam kontemporer itu kepada para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melalui kegiatan liqo, usrah, atau mentoring, kelak dari beberapa kegiatan itu melahirkan LDK hampir di semua kampus di Indonesia (Furkon, 2004).
Gerakan dakwah kampus awalnya berbasis di Masjid Salman (ITB) dalam waktu singkat menyebar ke berbagai perguruan tinggi lain, keberadaan masjid kampus bagi kegiatan LDK menjadi sangat vital bagi diseminasi ide-ide Islam di kalangan generasi muda Islam. Di dalam perkembangannya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) ini secara resmi menjadi organisasi kemahasiswaan intra kampus (Rubaidi, 2021).
KAMMI Dan Reformasi.
Ketika KAMMI dideklarasikan 29 Maret 1998, KAMMI menyatakan sikap politik diberi nama “Pandangan Umum KAMMI atas Berbagai Persoalan Bangsa Indonesia” setebal lima halaman, secara garis besarnya pandangan itu berisi. Pertama, krisis nasional merupakan tanggung jawab utama pemimpin. Kedua, menuntut dilaksanakannya reformasi total dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, hukum, budaya, dan moral). Ketiga, persoalan paling mendasar bangsa Indonesia adalah rusaknya nilai moral berbasis agama, kehancuran negeri serta pemerintahan akibat dari rusaknya nilai moral agama para pemimpin negeri ini (Sidiq, 2003).
Pasca dideklarasikan KAMMI bergabung bersama organisasi pergerakan mahasiswa lain turun di dalam aksi demonstrasi menuntut reformasi di berbagai kampus di seluruh Indonesia, salah satu aksi spektakuler KAMMI adalah demonstrasi besar-besaran di lapangan Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan yang melibatkan 20.000 massa mahasiswa pada 10 April 1998, inilah unjuk rasa mahasiswa pertama yang dilakukan di luar kampus, dengan partisipan aksi terbesar ketika itu (Rahmat & Najib, 2001). Kemudian KAMMI bersama Amien Rais menginisiasi menggelar Aksi Sejuta Massa di Lapangan Monas, Jakarta pada tanggal 20 Mei 1998, berbagai persiapan telah dilakukan termasuk mempublikasikan surat undangan terbuka bagi masyarakat umum untuk terlibat di dalam aksi, tetapi situasi terakhir di lapangan tidak memungkinkan aksi terjadi, mengingat respon penguasa sangat berlebihan dengan mengerahkan tentara disertai persenjataan berat mengelilingi Monas, akhirnya Aksi Sejuta Massa dibatalkan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Meskipun dibatalkan agenda aksi besar-besaran itu telah menjadi daya tekan luar biasa agar reformasi secepatnya terjadi (Sidiq, 2003).
Kemudian KAMMI bersama elemen mahasiswa lain melakukan aksi unjuk rasa dan pendudukan Gedung DPR/MPR RI mendesak reformasi di semua bidang dan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan selama 32 tahun.
Pasca kejatuhan Orde Baru eksistensi KAMMI mengalami perubahan dari wadah situasional pendorong gerbong reformasi menjadi organisasi kemahasiswaan (ormawa) ekstra kampus bersifat permanen, di dalam perjalanannya saat ini KAMMI telah menyentuh usia 27 tahun.
Referensi Artikel
1. Budiman, A. (2000). Kata Pengantar Catatan Perlawanan. In Catatan Perlawanan. Pustaka Pelajar.
2. Culla, A. S. (1999). Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. PT. Raja Grafindo Persada.
3. Damanik, A. S. (2002). Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia. Teraju.
4. Furkon, A. M. (2004). Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer. Teraju.
5. Huda, M. K. (2021). Al-Wala’ Wal Bara. Harakah Books.
6. Imam, R. (2016). Menyiapkan Momentum : Refleksi Paradigmatis Pemikiran Gerakan Pemuda Untuk Membangun Bangsa. Pustaka SAGA.
7. Maxwell, J. (2001). Soe Hok Gie : Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani. PT. Pustaka Utama Grafiti.
8. Rahmat, A., & Najib, M. (2001). Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus. Purimedia.
9. Rubaidi. (2021). Kelas Menengah dan Gerakan Islamisme di Indonesia. Intrans Publishing.
10. Sidiq, M. (2003). KAMMI Dan Pergulatan Reformasi Kiprah Politik Aktifis Dakwah Kampus Dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Era Intermedia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 2 months ago
45
2 months ago
45