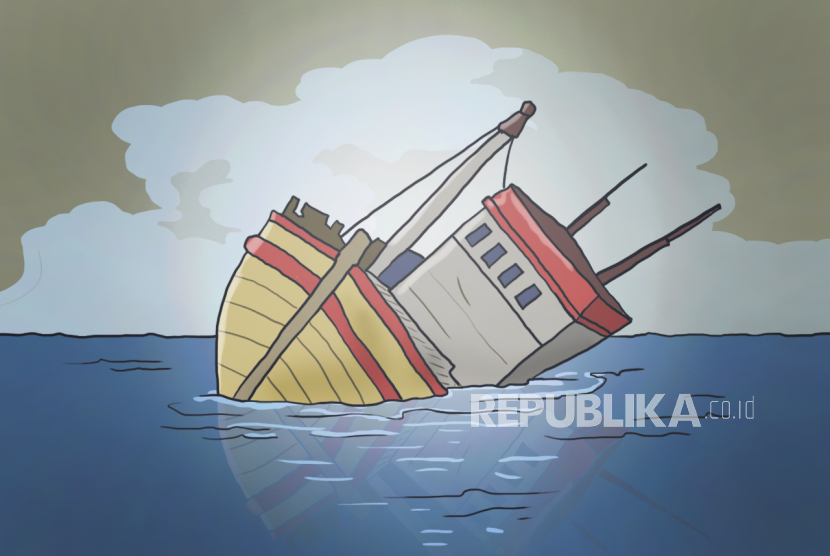Oleh : Dr Devie Rahmawati, CICS (Universitas Indonesia)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari ruang kuliah, kamar asrama, rumah ibadah, hingga ruang rapat perusahaan dan gedung parlemen — tubuh perempuan masih menjadi medan kekuasaan. Ia terus diperebutkan, dikendalikan, bahkan dirusak. Rentetan kasus di kampus-kampus besar hingga sejumlah pesantren menunjukkan satu hal: pelecehan seksual bukan sekadar penyimpangan individu. Ia adalah cermin dari “budaya” yang gagal menjaga martabat manusia.
Serial Unbelievable mengisahkan Marie Adler, korban pemerkosaan yang malah dipaksa mengaku berbohong oleh aparat penegak hukum. Sistem gagal memahami trauma dan justru menekan korban agar bungkam. Apa yang terjadi di layar itu, sayangnya, terasa sangat nyata di negeri ini. Kita melihat mahasiswi yang disalahkan karena rok yang dianggap “terlalu pendek”, atau santriwati yang dipaksa diam demi menjaga nama baik pesantren.
Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman — kampus, pesantren, bahkan kantor pemerintahan — justru sering menjadi arena impunitas. Reputasi institusi lebih dijaga daripada keselamatan manusia. Dalam Unbelievable, pelaku adalah pria biasa, seorang teknisi, yang memanfaatkan posisinya untuk masuk ke rumah korban. Ini paralel dengan kasus-kasus di Indonesia: pelaku bukan monster asing, melainkan orang yang dikenal, dihormati, bahkan diidolakan.
Salah satu adegan paling menyentuh dalam serial itu adalah ketika detektif perempuan berkata, “Korban tidak berbohong. Tapi sistem sering membuat mereka merasa harus berbohong.” Kalimat ini menampar kesadaran kita. Kita terlalu akrab dengan victim blaming — korban ditanya, “Apa yang kamu pakai?” alih-alih, “Apa yang dia lakukan padamu?”
Kita juga menyaksikan betapa pelaku dilindungi oleh institusi: dari Harvey Weinstein di Hollywood, hingga oknum-oknum di Indonesia yang cukup “dipindahkan jabatan”. Bahkan, teknologi kini ikut memperluas lingkup kekerasan: deepfake, revenge porn, dan rekaman tersembunyi menjadi senjata baru untuk merendahkan dan mengontrol perempuan — seperti kasus mahasiswa yang mengedit foto temannya hingga tampak telanjang.
Ketika seorang mahasiswa merekam tetangga kosnya yang mandi, seorang profesor melecehkan mahasiswa, dan seorang guru spiritual memperkosa santrinya — kita harus bertanya: Apa yang salah dari nilai-nilai yang kita wariskan?
Masyarakat kerap menyederhanakan kasus ini sebagai akibat lemahnya moral, pendidikan, atau hukum. Namun, faktanya, pelecehan terjadi di ruang yang justru dianggap paling bermoral, paling terdidik, dan paling religius. Salah satu sahabat Nabi pernah berkata, “Kekuasaan akan mengungkap siapa manusia sebenarnya.” Nyatanya, para pelaku kerap datang dari kalangan elit — mereka yang punya gelar, jabatan, atau kekuasaan.
Fenomena ini bukan khas Indonesia. Di Amerika Serikat, sejak 2017, tercatat 147 legislator di 44 negara bagian dituduh melakukan pelecehan seksual (PBS). Perusahaan raksasa seperti Uber dan Fox News kehilangan reputasi dan miliaran dolar karena membiarkan kekerasan seksual menjalar di dalam ruang kekuasaan (Harvard Business Review, BBC). Bahkan universitas sekelas Harvard dan Yale digugat karena menutupi kasus-kasus pelecehan (Koffels).
Kartini pernah berkata, “Tiada bangsa yang benar-benar merdeka jika setengah dari bangsanya masih direndahkan.” Ironisnya, hari ini, penjajahan terhadap perempuan datang bukan dari bangsa asing, melainkan dari masyarakat kita sendiri — masyarakat yang membiarkan kekerasan tumbuh di balik status dan jabatan.
Ancaman Baru di Era Digital
Di era digital, kekerasan semakin tak kasatmata. Laporan dari UN Women dan Dewan Eropa menunjukkan bahwa kekerasan berbasis teknologi — dari deepfake porn, perundungan siber, hingga gaslighting algoritmik — terus meningkat. Penelitian dari University College London (2024) membuktikan bahwa algoritma media sosial justru memperkuat penyebaran konten misoginis, terutama di kalangan remaja laki-laki.
Studi dari Tulane University (2023) menunjukkan bahwa meskipun gerakan #MeToo telah menggema ke seluruh dunia, angka kekerasan seksual di kampus dan tempat kerja tetap tinggi. Ini karena yang berubah baru permukaan — belum sistem, belum “budaya”.
Bung Karno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati hak-hak perempuan.” Maka, ukuran kemajuan bukanlah tinggi rendahnya gedung, canggihnya teknologi, atau jumlah gelar akademik. Peradaban diukur dari bagaimana kita memperlakukan kaum yang paling sering dibungkam.
Kita tidak sedang menghadapi kejahatan biasa. Ini adalah krisis budaya, krisis nilai. Sebuah keretakan struktural, ketika nama besar lebih penting dari kehormatan, dan kekuasaan lebih penting dari keadilan.
Dibutuhkan revolusi kultural. Bukan sekadar kampanye, tetapi pendidikan ulang. Bukan hanya reformasi hukum, tetapi perubahan cara pandang kolektif kita. Dibutuhkan keberanian nurani untuk mengatakan: cukup.
Nelson Mandela pernah mengingatkan, “Kebebasan sejati bukan hanya membebaskan diri sendiri, tetapi hidup dengan cara yang menghormati kebebasan orang lain.” Dan Rumi menulis, “Luka adalah tempat cahaya masuk.” Mungkin luka yang terus-menerus diderita perempuan ini akan menjadi jalan masuk cahaya bagi sebuah peradaban baru — jika kita cukup berani memperjuangkannya.
Tulisan ini adalah panggilan. Untuk berhenti menormalisasi kekerasan. Untuk membongkar “budaya” yang menyalahkan korban dan melindungi pelaku. Karena keadilan bukan hadiah dari negara atau agama — ia adalah warisan Ilahi yang harus diperjuangkan, bersama, sekarang juga!

 2 months ago
32
2 months ago
32