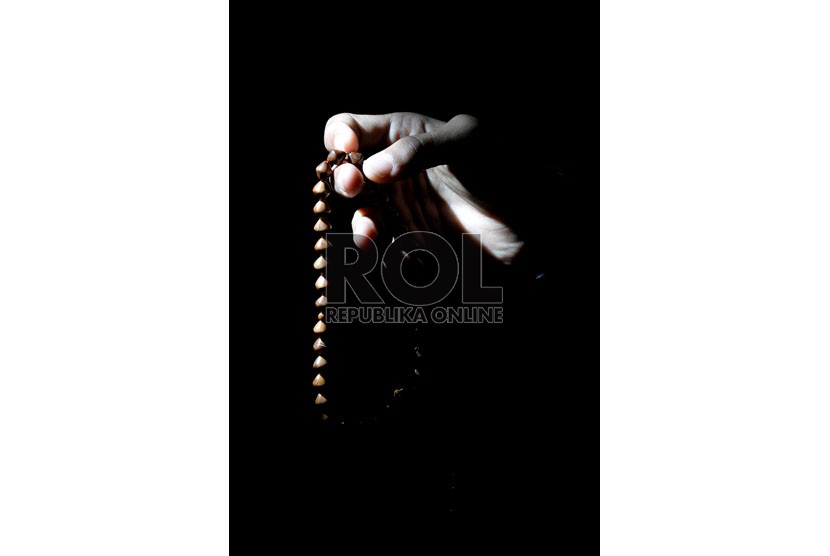Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Sejahtera 0,7. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Sejahtera 0,7. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kemarin di Senayan, gedung parlemen yang lebih mirip benteng ketimbang rumah rakyat karena pojok-pojoknya dijaga tentara, diketok palu: Undang-Undang APBN 2026 resmi disahkan. Anggaran, seperti biasa, defisit.
Yang mengejutkan bukan itu. Toh rakyat sudah kenyang dengan defisit yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti utang warisan keluarga yang tak pernah kita tanda tangani tapi harus kita bayar dengan pajak yang mencekik leher.
Yang bikin jidat berkerut adalah munculnya angka baru: Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) dipatok sebesar 0,7.
Nah, apa arti 0,7 ini? Apakah itu artinya petani kita hidupnya tinggal 70 persen layak, atau sisanya 30 persen hidup sambil pura-pura bahagia?
Kalau nilai rapor, angka 0,7 itu sama dengan 7 dari 10. Lumayanlah, tidak merah. Tapi kalau ini bicara nasib hidup 17 juta petani gurem, angka 0,7 lebih mirip rating warung kopi pinggir sawah di Google Maps: "Enak sih, tapi sering kehabisan gula."
Mari kita coba masuk ke contoh konkret. Sebut saja Makmur — bukan nama asli, karena kalau asli rasanya menyinggung. Makmur ini petani jagung di Jawa Timur yang hidupnya justru jauh dari makmur. Tahun lalu, hujan terlambat datang, pupuk raib entah ke mana.
Belum lagi hama menyerang lebih ganas dari komentar netizen di medsos. Hasil panennya anjlok, sementara anaknya butuh uang SPP. Kalau ditanya soal IKP 0,7, Makmur mungkin hanya garuk-garuk kepala sambil bertanya: “Itu bisa buat beli beras, nggak?”
Di Riau, ada juga Sabar, petani sawit yang lahannya kecil, hanya dua hektar, kalah jauh dibanding raksasa sawit yang punya ribuan hektar. Hasil kebunnya dijual murah ke pengepul, sementara harga pupuk naik lebih cepat daripada isi dompetnya.
Baca juga: Solusi Listrik Berkelanjutan, PLN Icon Plus Dukung Kementerian ESDM dan PLN
Kalau negara bilang IKP 0,7, Sabar mungkin menjawab lirih: "Kalau 0,7 itu skala Richter, sawah saya sudah ambruk."
Padahal BPS sudah sejak 2023 bikin survei untuk mengukur kesejahteraan petani. Jadi sebenarnya pijakannya ada. Pihak BPS sadar bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) yang lama hanya hitung-hitungan harga jual dan harga beli.
NTP terbatas: tidak bicara soal kesehatan, pendidikan, apalagi soal kualitas hidup. Nah, IKP ini katanya multidimensi: lihat pendapatan, gizi, akses pendidikan, hingga risiko gagal panen. Terdengar keren, mirip laporan PBB.
Tapi masalahnya, angka 0,7 yang dipatok dalam APBN 2026 itu maksudnya apa? Dan nanti siapa yang benar-benar merasakan? Apakah itu hanya angka-angkaan untuk keren-kerenan bahwa kita sudah punya indeks yang menghitung kesejahteraan petani?
Baca juga: Potensi Penerimaan, Pemkot Depok Targetkan PAD Rp3 Triliun
Sebab, mari kita jujur: lebih dari 60 persen petani Indonesia itu gurem, seperti Makmur, yang lahannya rata-rata di bawah 0,5 hektar. Bandingkan dengan segelintir konglomerat agraria yang lahannya seluas drone memandang.
IKP 0,7 untuk petani kecil sama artinya dengan memberi harapan palsu. Itu kayak bilang, “Tenang, kamu sudah sejahtera versi statistik,” padahal di dapurnya cuma ada mi instan yang diirit untuk dua kali makan.
Pertanyaannya: apakah kita memang perlu indeks semacam ini? Atau jangan-jangan indeks hanyalah cara elegan negara untuk menutup mata, sambil berkata: “Lihat, kami sudah mengukur kesejahteraan petani, angkanya jelas, 0,7!”
Padahal yang dibutuhkan petani bukan angka IKP, tapi akses lahan, pupuk murah dan mudah didapat, harga panen yang adil, bebas dari mafia tengkulak, serta tentu saja keberpihakan kebijakan yang nyata dari pemerintah.
Baca juga: Mahasiswa Vokasi UI Berprestasi di Oregon Screams Horror Film Festival Fall 2025
Namun, jangan buru-buru sinis. Indeks ini boleh jadi tetap penting. Ia bisa jadi peta, bukan tujuan. Tanpa peta, kebijakan pertanian sering nyasar: mau membantu petani kecil, eh yang dapat malah perkebunan besar.
Dengan IKP, pemerintah bisa ditodong: “Hei, IKP masih 0,7, kapan jadi 1,0?” Artinya, indeks ini bisa jadi alat kontrol publik. Tapi, lagi-lagi, indeks tak bisa dimakan. Sama seperti Anda punya sertifikat vaksin, tapi masih harus bayar obat sendiri di apotek.
Akhirnya, kita kembali ke tragedi klasik: petani yang memberi makan bangsa, justru paling sering lapar. Tragedi itu memang pahit, tapi dalam kepahitan itu kadang ada tawa getir. Kalau tidak sejahtera, setidaknya mereka merasa bahagia dengan tertawa-tawa.
Angka 0,7 bisa kita anggap sebagai nilai ujian negara dalam menyejahterakan petani. Nilai cukup, tapi nyaris remedial. Dan seperti anak sekolah yang nakal, negara kita sering bangga dengan angka pas-pasan itu.
Baca juga: Catatan Cak AT: Aktivis Rasa Kerupuk
Jadi, mari kita belajar tertawa di tengah ironi: ternyata kesejahteraan petani bisa dihitung, dibulatkan, bahkan diumumkan di gedung parlemen dengan segala wibawa. Bahwa, bangsa Indonesia baru saja, setelah 80 tahun merdeka, punya IKP.
Yang tak bisa dihitung adalah kesabaran dan kemakmuran para petani kecil yang tetap bangun jam lima pagi, mencangkul tanah, menanam benih, berharap pada langit, dan akhirnya berdoa agar hidupnya tidak sekadar jadi angka di tabel BPS.
Karena, bukankah hidup petani lebih berharga dari sekadar 0,7? (***)
Penulis: Cak AT - Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 24/9/2025

 2 months ago
25
2 months ago
25