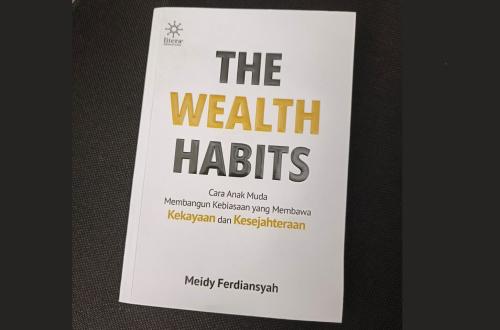Oleh : Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS (Konsultan ESG dan Produktivitas serta Anggota IS2P & ICSP)
REPUBLIKA.CO.ID, Di belahan dunia lain, lonceng peringatan itu telah berbunyi nyaring. Dave Jones, dalam tulisannya yang tajam di Yale Law Journal Forum (Desember 2025), menyebut asuransi sebagai “burung kenari di tambang batu bara” bagi krisis iklim. Ketika burung kenari berhenti bernyanyi, maka ketika itu pula perusahaan asuransi berhenti menanggung risiko. Ini tandanya bahaya mematikan sudah di depan mata.
Kita melihat buktinya pada kebakaran hutan dahsyat di Los Angeles awal 2025 yang menelan kerugian ekonomi hingga ratusan miliar dolar AS. Namun, bagi kita di Jakarta, ancaman itu tidak datang dari api, melainkan air. Dan tahun 2026 ini bukan lagi waktu untuk sekadar berwacana.
Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2025, industri asuransi umum dituntut memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko material yang timbul dari faktor eksternal dan perubahan lingkungan bisnis, yang secara implisit mencakup risiko terkait perubahan iklim.
Pertanyaannya sederhana, namun mengerikan: seberapa siap neraca keuangan asuransi kita jika langit Jakarta menumpahkan hujan yang belum pernah kita lihat sebelumnya?
Matematika bencana: bukan sekadar tebak-tebakan
Selama ini, banyak praktisi asuransi berlindung di balik data historis. “Banjir besar hanya terjadi lima tahun sekali,” begitu mantra yang sering diucap. Namun, studi skenario pembatas (bounding scenarios) oleh Kousky dkk. (2024) mengingatkan kita bahwa perubahan iklim menciptakan risiko yang “tanpa preseden”. Data masa lalu bukan lagi cermin yang jujur untuk masa depan.
Untuk menjawab keraguan ini, saya melakukan simulasi stress test kuantitatif pada portofolio asuransi properti dan kendaraan bermotor di Jakarta, menggunakan parameter skenario Hot House World dari Network for Greening the Financial System (NGFS) untuk tahun 2030. Hasilnya bukan sekadar angka, melainkan sebuah peringatan keras.
Dalam simulasi tersebut, kita asumsikan kenaikan curah hujan ekstrem “hanya” sebesar 25 persen. Bagi orang awam, angka ini mungkin terdengar kecil. Namun, dalam hidrologi, ada efek pengali (multiplier).
Kenaikan curah hujan 25 persen tidak berarti genangan air naik 25 persen. Berdasarkan model damage function yang saya terapkan, kenaikan curah hujan tersebut diterjemahkan menjadi faktor pengali banjir sebesar 1,4 kali lipat. Artinya, genangan air menjadi jauh lebih dalam dan merusak.
Dampaknya pada kantong perusahaan asuransi sangat mengejutkan. Dari simulasi portofolio hipotetikal senilai total pertanggungan (TIV) tertentu di lima zona risiko Jakarta (dari Pluit hingga Cawang), lonjakan klaim bruto (gross loss) meroket dari Rp6,85 miliar pada skenario normal menjadi Rp17,07 miliar pada skenario tekanan iklim.
Setelah dikurangi deductible nasabah dan pemulihan reasuransi (XoL), beban klaim bersih (net claim) yang harus ditanggung perusahaan melonjak drastis. Kenaikan beban klaim bersih tercatat mencapai 64,8 persen. Bayangkan, hanya karena hujan bertambah seperempat, uang yang harus dikeluarkan perusahaan melonjak hampir dua pertiga. Ini adalah profitability shock yang nyata.

 3 hours ago
8
3 hours ago
8