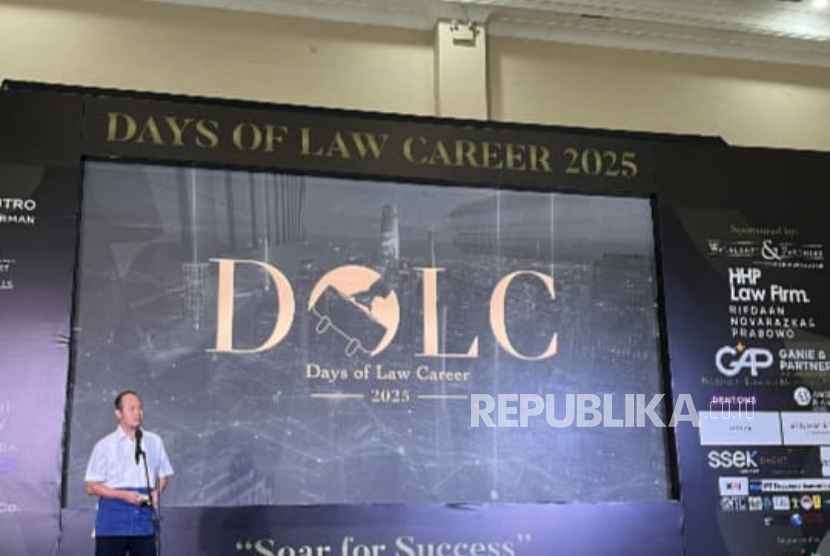Oleh : Aslichan Burhan, Direktur PINBUK ICMI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terlepas dari yang tidak cocok, dalam waktu singkat popularitas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melesat. Gaya komunikasinya yang blak-blakan, pendek, dan gampang nyantol terasa seperti “kuliah umum”. Bukan kuliah formal tentu—ini kuliah publik: potongan pernyataan yang mengajari publik prinsip ekonomi praktis sambil membuka arah kebijakan fiskal pemerintahan.
Dampaknya? Percakapan finansial yang tadinya eksklusif jadi lebih membumi; “kepercayaan public” yang jadi modal awal tiap kebijakan dukungan publik menguat.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.“Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus… penerimaan ikut kencang,” katanya ketika menepis wacana pajak baru. Intinya: target pendapatan digenjot lewat pertumbuhan, bukan menaikkan tarif atau menambah jenis pajak. Ini masuk akal bagi pelaku usaha dan rumah tangga—stabilitas aturan pajak memberi ruang bernapas sambil pemerintah fokus menutup kebocoran dan memperluas basis. Pernyataan senada kembali ia tegaskan: tak perlu pajak baru; optimalkan yang sudah ada.
Di sisi "konsumsi rakyat", Purbaya bicara gamblang dan viral soal gaya hidup dan literasi finansial. “Belanja enggak apa-apa… tapi sesuaikan dengan kantong. Jangan ngutang.” Ia menyambung dengan pesan untuk anak muda agar “jangan FOMO” (takut tertinggal dengan tren); pahami instrumen sebelum berinvestasi. Ini bukan jargon motivasi; ini edukasi kebijakan: fiskal menjaga daya beli, masyarakat dibekali etika konsumsi dan disiplin investasi. Responnya luas—dari media sampai warganet—karena bahasanya nyambung dan bisa dipraktikkan besok pagi.
Soal "pajak tak naik", ia bahkan membuka opsi penyesuaian PPN yang pro-daya beli. “Nanti kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli,” ujarnya di forum resmi. Publik menangkap sinyal: ruang kebijakan akan dipakai untuk mendorong mesin konsumsi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
“Uang harus berputar” adalah kuliah singkat lain yang langsung diikuti aksi. Pemerintah memindahkan dana likuid Rp200 triliun dari BI ke bank-bank Himbara untuk menambah pasokan kredit, menurunkan biaya dana, dan mendorong aktivitas sektor riil. “Kalau kurang kita tambah lagi,” katanya—sekaligus menandai kebijakan yang data-driven dan outcome-based. Ini bukan sekadar wacana: penempatan dana dilaporkan cepat terserap, dan komunikasi berkala ke publik dibuat agar ekspektasi pasar terjaga.
Lalu ada “kuliah” disiplin belanja negara_. Purbaya memberi tenggat ke Kementerian/Lembaga (K/L): serap anggaran sekarang, atau siap realokasi untuk tujuan yang lebih mendesak—termasuk mengurangi kebutuhan utang. “Akhir Oktober saya akan lihat lagi, kalau enggak ada yang maju ya saya ambil lagi duitnya,” tegasnya. Pesan ini menular ke level daerah: ia menyoroti ratusan triliun dana pemda yang mengendap di perbankan—uang yang seharusnya bekerja untuk layanan publik. Publik menangkap dua hal: pemerintah serius mempercepat belanja produktif, dan dana “parkir” akan didorong kembali ke ekonomi riil.
Di titik inilah Buya Anwar Abbas Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI memberi bingkai etika yang menggema di media sosial. Ia menyebut langkah “memfungsikan uang”—menarik dana yang menganggur dari BI ke perbankan agar beredar ke rakyat—sejalan dengan larangan praktik iktinaz (menimbun uang) dalam perspektif fikih muamalah. Bahasa sederhananya: uang jangan didiamkan; harus mensejahterakan. Harmoni antara fiskal nyata dan etika syariah ini membuat kebijakan terasa nyambung bagi khalayak luas—bukan hanya ekonom.
Sisi lain kuliah publik Purbaya adalah rule of the game: yang bisnis, ya diselesaikan secara bisnis. Ia menolak APBN dipakai membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh; logikanya, jika keuntungan BUMN dihimpun oleh holding investasi (Danantara), maka penyesuaian kewajiban juga ditangani ekosistem yang sama—bukan dibebankan ke kas negara. Pesan ini mengajarkan disiplin fiskal kepada publik dan pelaku: risiko harus match dengan pengambil keputusan dan penerima manfaatnya.
Bagian yang tak kalah penting: sinkronisasi fiskal-moneter. Purbaya menegaskan kekompakan dengan Gubernur BI; koordinasi intens untuk menjaga stabilitas sekaligus mendongkrak pertumbuhan. Narasi “satu orkestra” ini krusial agar pasar tidak membaca policy mix yang saling bertolak belakang—lagi-lagi sebuah kuliah singkat tentang pentingnya kejelasan arah. Di ranah investasi, ia menggelar “gelar perkara mingguan” bersama pelaku pasar dan perbankan untuk mengurai hambatan satu per satu—pendekatan problem-solving yang mengubah keluhan jadi daftar kerja.
Di internal Kemenkeu, Purbaya juga memulai dengan… telepon dan sidak. Ia beberapa kali “ngetes” langsung Kring Pajak 1500200 dan menyambangi pusat layanannya—memeriksa kualitas respons, waktu tunggu, sampai prosedur eskalasi aduan. Buat publik, gaya ini terasa sebagai “kuliah praktek” tentang manajemen layanan: jangan percaya laporan di atas kertas sebelum Anda menyimak suara pengguna di ujung telepon. Untuk Ditjen Pajak, pesan tak tersiratnya jelas—perbaiki titik kontak wajib pajak dulu, baru bicara target besar.
Dari sidak front-line, ia naik ke “mesin inti”: proyek Core Tax Administration System (PSIAP/CTAS). Sejak awal menjabat, Purbaya menilai arsitektur dan implementasinya belum memberikan dampak setara dengan biaya dan ekspektasi, bahkan perbaikan dan penguatan sistem diakui molor ke 2026. Dengan backgroundnya dari Teknik Elektro ITB yang tentu paham system dan aplikasi, ia mendorong audit desain, governance vendor–termasuk konsorsium pengembang dan “hacker” —untuk pengetesan yang lebih keras agar sistem benar-benar mempermudah kepatuhan, memperkecil error, serta mempercepat restitusi dan keberatan. Intinya: agar Core Tax menjadi “enabler” penerimaan, bukan “bottleneck”.
Di lapangan, ia tak ragu mengoreksi langkah yang berpotensi membebani dunia usaha kecil. Penundaan implementasi kebijakan pajak tertentu di e-commerce, misalnya, dibaca publik sebagai tanda sensitivitas pada momentum pemulihan—sementara penegakan terhadap pelanggaran dan kebocoran tetap digenjot. Tone kebijakan seperti ini menyampaikan pelajaran sederhana: negara tegas pada kebocoran, tetapi menghindari policy shock pada sektor yang rentan.
Tak semua kuliah manis—dan memang tak perlu. Tuntutan publik terhadap ucapannya pada hari-hari awal menjabat dijawab dengan permintaan maaf terbuka. Alih-alih defensif, ia balik menjadikan momen itu sebagai pelajaran komunikasi kebijakan. Secara pendidikan publik, ini penting: policy maker yang bisa merevisi sikap memberi contoh bahwa kebijakan adalah proses belajar—bukan kebenaran yang sudah selesai.
Di media sosial, potongan videonya yang mengajak “kita sama-sama menjadi kaya bersama” menjadi semacam hook emosional. Banyak yang menertawakan, tak sedikit yang merasa ikut diberi harapan. Namun jika dipilah dari sisi substansi, ajakan itu kompatibel dengan kebijakan dasarnya: dorong pertumbuhan, jaga daya beli, dan perluas akses pembiayaan agar pelaku usaha—terutama UMKM—bisa naik kelas. Inilah mengapa satu kalimat populis bisa nyetrum ketika selaras dengan perangkat kebijakan di belakangnya.
Apa efek pembelajaran bagi masyarakat? Pertama, publik makin paham bahwa fiskal bukan hanya soal “naik-turun pajak”, tetapi juga soal timing dan sirkulasi uang: kapan uang negara harus cepat dipakai, kapan harus ditahan; bagaimana uang yang menganggur malah bikin ekonomi seret; kenapa insentif salah tempat bisa merusak disiplin. Kedua, pelaku usaha melihat sinyal: pemerintah akan mengalihkan anggaran dari program yang lambat atau tak efektif ke program yang berdampak. Ini mendorong kompetisi kualitas program—bukan sekadar besarnya pagu. Ketiga, rumah tangga menangkap etika dan manajemen keuangan praktis: kendalikan utang konsumtif, belajar instrumen, dan investasikan kelebihan kas secara bertahap. Satu lagi menurut saya bisa ditambahkan, investasi keuangan sosial dalam bentuk zakat/wakaf yang dalam perspektif Ilahiyah yang memberikan dampak paling dahsyat.
Di level ekosistem, kuliah publik ini memperlihatkan playbook yang relatif konsisten: stabilitas (tidak menambah jenis pajak sembarangan), dorong pertumbuhan (opsi penyesuaian PPN secara terukur), percepat sirkulasi uang (penempatan dana SAL di Himbara, dorongan belanja K/L dan pemda), perkuat koordinasi BI-Kemenkeu, dan jaga disiplin fiskal (risiko bisnis ditanggung entitas bisnis). Di luar negeri, kanal pembiayaan dan investasi juga terus dibina; misalnya, negosiasi utang Whoosh diarahkan lewat jalur korporasi/BUMN dan komunikasi dengan mitra Tiongkok, sementara pemerintah pusat fokus menjaga fiskal tetap sehat—pesan yang dibaca positif oleh pelaku pasar.
Hemat saya, materi paling penting dari “kuliah umum” Purbaya adalah cara ia membagi peran: 1) pemerintah mendorong arus uang untuk belanja publik & sektor riel diikuti tutup kebocorannya; 2) perbankan menyalurkan kredit pembiayaan secara bertanggung jawab; 3) dunia usaha mengeksekusi investasi; 4) warga mengelola keuangan dengan nalar yang sehat. Itulah kenapa dukungan moral dari tokoh seperti Buya Anwar Abbas terasa nyambung—kebijakan fiskal yang memfungsikan uang bertemu etika ekonomi yang melarang penimbunan, iktinaz. Di titik ini, publik tidak hanya disuruh percaya; publik diajak paham.
Tentu, pekerjaan rumahnya tidak kecil. Penempatan dana jumbo harus diawasi agar benar-benar mengalir ke kredit produktif, bukan hanya numpang parkir di aset keuangan; penurunan PPN—jika diambil—wajib diimbangi sistem yang mudah dan memadai, perbaikan kepatuhan dan penegakan agar basis pajak tak rontok; percepatan belanja harus fokus ke "program yang paling menghasilkan bang for the buck”; dan koordinasi dengan BI mesti menjaga ekspektasi inflasi tetap terjaga. Di wilayah proyek infrastruktur berisiko, disiplin “yang bisnis, diselesaikan bisnis” harus konsisten, termasuk ketika tekanannya bersifat politis. Tapi kalau kuliah-kuliah publik ini berlanjut—terbuka, pakai data, dan berani menerima koreksi—maka publik punya alasan rasional untuk optimistis.
Pada akhirnya, yang membuat “kuliah” ini bergaung bukan karena slogannya, melainkan karena publik melihat *benang merah antara kata dan kerja*: tidak asal memungut, tapi menguatkan mesin pertumbuhan; tidak memanjakan, tapi menegakkan disiplin; tidak menimbun, tapi menggerakkan. Konsistensi itu mesti dirawat, ajakan kita kaya bersama” mesti diikuti rencana kerja yang setiap waktu bisa diukur kemajuannya. Dan ketika masyarakat merasa diajak paham ketimbang sekadar patuh, pelan-pelan kita membangun kesadaran fiskal bersama: "uang publik kembali bekerja untuk publik". Insya Allah.

 2 months ago
33
2 months ago
33