 Muliadi Saleh
Muliadi Saleh
Gaya Hidup | 2025-09-17 12:55:58
Penulis : Muliadi Saleh

Kata urban lahir dari bahasa Latin urbs yang berarti kota. Ia menandai sebuah ruang yang berbeda dari pedesaan. Kota adalah ruang kepadatan, bangunan yang menjulang, jalan beraspal, denyut ekonomi yang cepat, dan irama hidup yang jarang memberi ruang bagi tanah untuk bernapas. Sebaliknya, pedesaan adalah ruang di mana tanah tetap menjadi panggung utama kehidupan. Di sana, kabut subuh masih turun di pematang sawah, ayam jantan membangunkan hari, dan pertanian menjadi denyut yang menenun hubungan manusia dengan alam. Maka, ketika kata urban dipadukan dengan farming, lahirlah istilah yang pada mulanya terasa paradoksal: pertanian di tengah kota, bercocok tanam di antara beton, baja, dan aspal.

Namun sejarah menunjukkan, paradoks itu sesungguhnya sudah tua. Di Mesopotamia kuno, sekitar 3500 tahun sebelum masehi, warga kota telah mengalokasikan lahan di dalam tembok kota untuk bercocok tanam. Di lembah Meksiko, bangsa Aztek mengembangkan chinampa—pulau buatan di atas danau—yang menjadi salah satu bentuk urban agriculture paling produktif sepanjang sejarah. Bahkan di kota-kota Eropa pasca Perang Dunia, taman kota dan halaman rumah digunakan untuk produksi pangan darurat. Urban farming lahir bukan dari tren semata, melainkan dari kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup dan menjaga keterhubungan dengan pangan.

Di Indonesia sendiri, jejak urban farming kian nyata. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) menjadi tonggak awal bagaimana rumah tangga di kota memanfaatkan ruang sempit untuk menanam. Sebuah penelitian di Bandung Utara menunjukkan bahwa rumah tangga yang aktif melakukan urban farming mengalami penurunan ketidakamanan pangan dan berkurangnya pengeluaran belanja makanan. Bahkan, pada keluarga yang dipimpin perempuan, hasil kebun pekarangan memberi tambahan penghasilan nyata. Artinya, urban farming tidak hanya soal estetika hijau kota, tetapi benar-benar berhubungan dengan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Jika membandingkan berkebun di pedesaan dengan di perkotaan, jelas terlihat perbedaan yang mendasar. Di desa, lahan masih terbentang luas, tanah subur mudah dijangkau, air mengalir dari sungai atau sumur, dan musim menjadi penentu ritme kehidupan. Pertanian di pedesaan sering berskala besar, baik sawah padi, ladang jagung, atau kebun kopi. Di sana, hasil panen bukan hanya untuk keluarga, melainkan juga untuk pasar regional dan bahkan ekspor. Budaya bercocok tanam di pedesaan erat dengan tradisi, ritual, dan kebersamaan komunitas. Petani desa adalah pewaris pengetahuan panjang tentang tanah, cuaca, dan keanekaragaman hayati.
Di kota, lanskapnya berbeda sama sekali. Lahan luas adalah kemewahan yang jarang ada. Pekarangan sering kali hanya sepetak tanah di belakang rumah, atau bahkan sekadar deretan pot di balkon dan atap. Polusi udara, keterbatasan air bersih, dan suhu panas kota menjadi tantangan tambahan. Karena itu, urban farming lahir dalam bentuk inovatif: hidroponik, vertikal farming, aquaponik, hingga pemanfaatan dinding dan atap sebagai ruang tanam. Produksinya lebih kecil, tetapi punya nilai lebih: menyediakan sayuran segar untuk keluarga, mengurangi jarak distribusi pangan, dan memberi keindahan serta ruang sosial baru di tengah kota.

Perbedaan lain terletak pada orientasi budaya. Jika di desa pertanian adalah warisan turun-temurun, di kota ia sering lahir sebagai bentuk resistensi terhadap keterasingan dari alam. Menanam cabai di pot atau selada di pipa hidroponik adalah cara warga kota untuk kembali bersentuhan dengan tanah dan air, untuk mendekatkan anak-anak mereka dengan asal usul makanan, dan untuk menghadirkan makna baru tentang keberlanjutan. Urban farming menjelma bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah gerakan sosial, pendidikan, dan bahkan spiritual.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan, jika urban farming dikelola dengan baik, ia bisa memenuhi 30 hingga 40 persen kebutuhan pangan kota baru seperti Ibu Kota Nusantara. Artinya, urban farming bukan sekadar pelengkap, tetapi strategi nyata dalam menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Lebih jauh, riset yang dilakukan oleh Diana Hertati dan koleganya menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap urban farming semakin baik. Kendati masih menghadapi hambatan modal, keterampilan teknis, serta cuaca ekstrem, tren ini menegaskan bahwa warga kota makin menyadari pentingnya kemandirian pangan.

Farming sendiri, bila dilihat lebih luas, tidak berhenti pada aktivitas menanam. Ia adalah sistem yang mencakup seluruh siklus pangan: mulai dari benih, pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, panen, distribusi, hingga meja makan. Farming juga adalah ekologi, karena ia menyangkut keberlanjutan tanah dan air. Ia adalah budaya, sebab pangan bukan sekadar kalori melainkan identitas yang merangkul tradisi dan kebersamaan. Ia adalah ekonomi, sebab dari pertanian lahir penghidupan dan pekerjaan. Dan ia adalah ruang sosial, sebab di kebun—baik di desa maupun kota—manusia belajar tentang kesabaran, kebersamaan, dan harapan.
Maka, urban farming adalah puisi yang tumbuh di antara beton dan kaca. Ia adalah jawaban atas kota yang kian terputus dari tanah. Ia adalah cara sederhana untuk menghadirkan kembali hubungan antara manusia, alam, dan pangan. Bila di desa embun pagi jatuh di pematang sawah, maka di kota ia menempel di daun selada yang tumbuh di balkon. Bila di desa panen adalah pesta rakyat, maka di kota panen tomat di atap rumah adalah pesta kecil keluarga. Tetapi esensinya sama: manusia merayakan kehidupan melalui tanah dan tanaman.
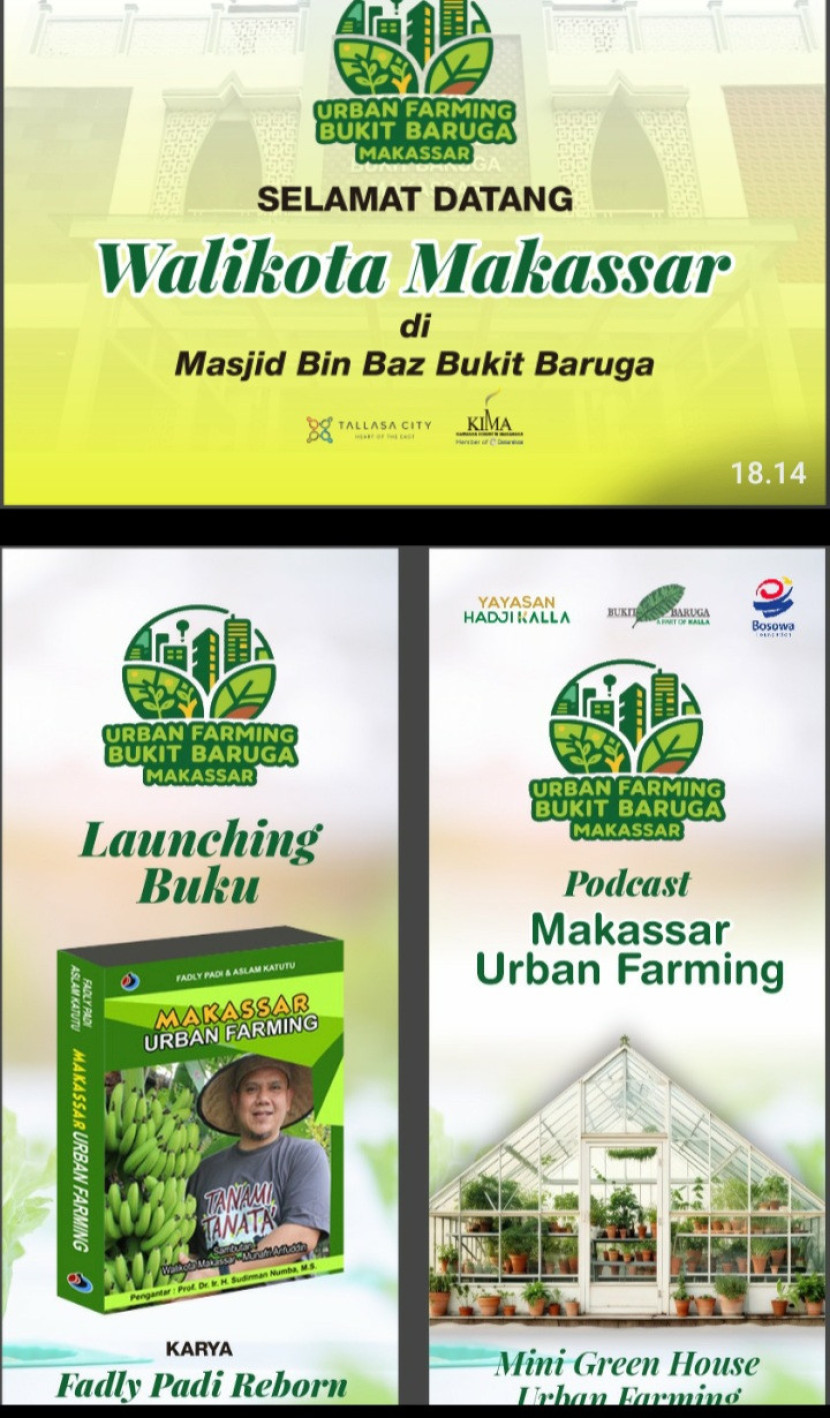
Pada akhirnya, urban farming bukan sekadar tren, melainkan refleksi tentang masa depan. Dunia menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan urbanisasi yang kian masif. Kota-kota tumbuh, desa-desa mengecil. Maka, kemampuan kota untuk menanam kembali, meski dalam ruang sempit, adalah tanda bahwa manusia tidak menyerah. Urban farming adalah ingatan kolektif yang dihidupkan kembali: bahwa kehidupan sejati selalu bermula dari tanah, dari benih kecil yang tumbuh, dan dari tangan yang mau merawatnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 2 months ago
33
2 months ago
33













































