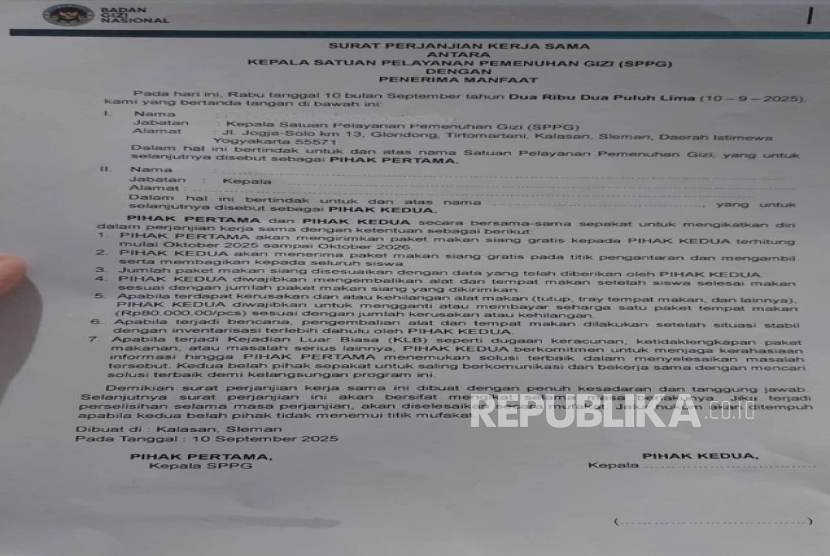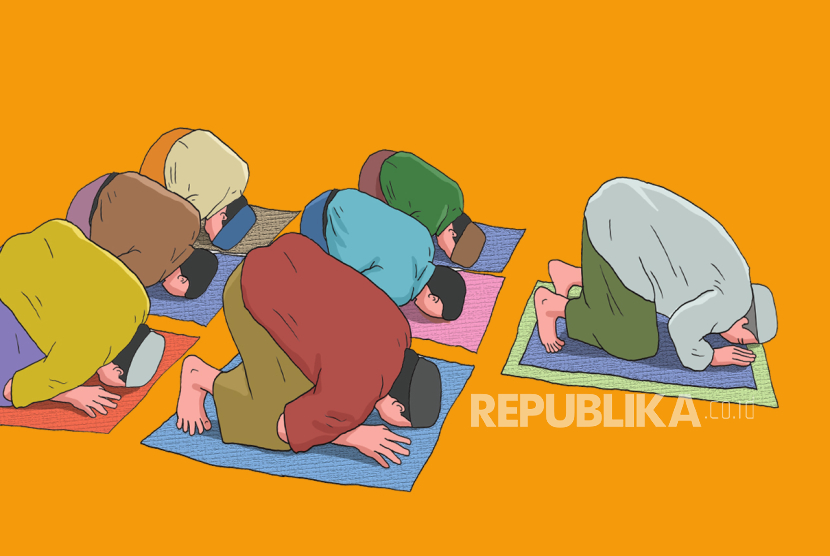Oleh : Nasihin Masha, Wartawan Senior
REPUBLIKA.CO.ID,
Bung Hatta, proklamator Indonesia bersama Bung Karno, pernah menulis, bahwa pada suatu masa akan hadir zaman besar tapi yang muncul orang kerdil. Maksudnya adalah, masa ketika peluang untuk maju begitu terbuka bagi Indonesia, tapi justru yang muncul adalah pemimpin-pemimpin kerdil. Mereka orang-orang yang tak pantas memimpin karena hanya akan membawa pada kemunduran. Bung Hatta menulis dalam konteks kemerdekaan Indonesia sebagai zaman besar, namun jembatan emas (istilah ini dari Bung Karno) kemerdekaan tersebut justru menjadi pintu bermunculannya manusia-manusia kerdil yang di masa perjuangan justru bersembunyi. Kini, zaman besar itu adalah reformasi. Setelah Indonesia lepas dari represi Orde Baru, justru melahirkan manusia-manusia kerdil.
Karena itu, Plato – seorang filsuf Yunani pada 2.500 tahun lalu – telah membuat syarat yang ketat bagi seorang pemimpin negara/pemerintahan, yaitu yang ia namakan kaloskagathos: elok dan baik. Dan untuk bisa sampai ke sana, seorang pemimpin harus dididik dari sisi rasa, fisik, penalaran, dan karakternya. Untuk itu mereka diajarkan tentang seni musik, olahraga, matematika, dan filsafat. Seorang pemimpin harus memiliki cita rasa dan kehalusan budi, fisik yang prima, kemampuan berpikir yang mumpuni, dan sikap bijak. Di sini, Plato tidak mensyaratkan popularitas dan kekayaan. Karena itu, menurutnya, seorang pemimpin negara/pemerintah harus seorang filsuf. Untuk itu, Plato membangun academia yang mendidik calon-calon pemimpin. Para bangsawan dan raja mengirim anak-anaknya untuk dididik Plato.
Bisa jadi kita mengatakan bahwa itu kan situasi 25 abad lampau. Di sini perlu diingat bahwa benih negara republik dan demokrasi justru tumbuh dari masa Yunani Kuno. Dan, Plato mengemukakan gagasannya dalam bukunya yang berjudul Republik. Jadi, gagasan Plato tetap relevan, khususnya tentang syarat-syarat seorang pemimpin. Apalagi ketika situasi abad ke-21 ini sedang didera disrupsi digital. Semua orang memiliki akses informasi secara langsung di genggaman tangan melalui handphone. Akibatnya, politik elektoral diterjang algoritma informasi karena kuatnya kendali media sosial dalam memengaruhi opini dan persepsi – yang akhirnya memengaruhi pilihan – publik dalam hal apapun. Faktual dan hoax menjadi tak jelas batasnya, benar dan salah menjadi tak jelas ukurannya. Yang menang adalah yang mampu memaparkan opininya ke banyak orang.
Bersekutu dengan Kemiskinan
Kemiskinan adalah ibu dari penyakit sosial dan dekadensi. Jika pertumbuhan ekonomi menurun maka tingkat kriminalitas pasti akan meningkat. Itu hukum alam. Ini bukan berarti orang miskin adalah bandit dan orang yang lebih kaya adalah orang baik. Tidak. Di tengah situasi kemiskinan juga akan melahirkan manusia kaya yang memanfaatkan kondisi kemiskinan. Terlalu banyak orang yang ingin lepas dari kemiskinan dengan menjadi budak harta. Dan orang kaya hapal harga masing-masing kepala orang-orang miskin yang bisa menjadi jejaring kriminalnya: menjadi kaki tangan, menjadi objek suap, menjadi informan, menjadi tukang jilatnya, menjadi tukang pukul, dan seterusnya. Karena itu, negara dengan kemiskinan akut akan dipenuhi fenomena mafia, warlord, premanisme, korupsi, dan sebagainya.
Dalam dunia politik, orang itu bisa menjadi pialang atau investornya. Ia akan mencari boneka dan budaknya. Pada ambisi puncaknya ia siap untuk menjadi aktor tunggal yang memonopoli semuanya. Dengan cara itu ia akan menciptakan kerajaan kekuasaan dan kerajaan harta di atas kubangan kemiskinan sambil pencet sana pencet sini, injak sana injak sini. Lalu dihiasi dengan ornamen altruisme dengan membangun fasilitas ini-itu dan bagi uang ke sana ke mari. Namun tetap saja semua berdiri di atas pijakan banditisme.
Bank Dunia merilis bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 171,8 juta jiwa, yang mencakup 60,3 persen dari total penduduk Indonesia. Angka itu diraih dengan standar pengeluaran 6,85 dolar AS per kapita per hari. Standar ini berarti memasukkan Indonesia ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas – ada 37 negara di dunia. Kurs nya bukan kurs nilai tukar tapi kurs purchasing power parity, yaitu daya beli antarnegara (yaitu 1 dolar AS = Rp 5.993,03). Angka ini tentu berbeda dengan angka resmi dari pemerintah Indonesia (dh/i Badan Pusat Statistik). Menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 24,06 juta jiwa, atau hanya 8,57 persen dari total populasi.
BPS mengakui bahwa Indonesia memang sudah masuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas. Gross National Income per kapita Indonesia pada 2023 sudah mencapai 4.870 dolar AS. Namun BPS mengingatkan bahwa rentang negara berpendapatan menengah ke atas adalah dari 4.516 dolar AS hingga 14.005 dolar AS. Jadi posisi Indonesia hanya sedikit di atas batas bawah. Karena itu, memasukkan Indonesia dengan standar 6,85 dolar AS per kapita per hari menjadi terlalu tinggi untuk Indonesia. Akibatnya, jika mengikuti kriteria Bank Dunia menjadikan jumlah penduduk Indonesia menjadi sangat besar. BPS juga mengingatkan bahwa dengan standar yang diterapkan BPS, di atas garis kemiskinan masih ada kelompok rentan miskin (24,42 persen atau 68,51 juta jiwa), menuju kelas menengah (49,29 persen atau 138,31 juta jiwa), kelas menengah (17,25 persen atau 48,41 juta jiwa), dan kelas atas (0,46 persen atau 1,29 juta jiwa). Garis kemiskinan (GK) nasional Indonesia per kapita per bulan adalah Rp 595.242. Sedangkan untuk rentan miskin 1 – 1,5 GK, menuju kelas menengah 1,5 – 3,5 GK, kelas menengah 3,5 – 17 GK, dan kelas atas 17 GK.
Namun perlu diingat, hingga kini, BPS belum mengubah kriteria sejak 1998. Memang angka GK nya terus berubah setiap tahun. Namun penetapan batas garis kemiskinan Rp 595.242 per kapita per bulan juga terlalu kecil, hanya sekitar Rp 20 ribu per kapita per hari. Mungkin dengan membagi kelompok miskin dan rentan miskin maka sebetulnya angka realistis orang miskin adalah gabungan orang miskin dan rentan miskin tersebut, sehingga angkanya menjadi 92,57 juta jiwa atau 32,99 persen. Angka gabungan ini sebagai kelompok miskin menjadi sangat realistis. Hal ini paling mudah dibuktikan pada masa pemilu atau pilkada. Money politics dan politik bansos begitu efektif dalam menentukan elektabilitas. Hal ini sebetulnya “secara resmi” diakui pemerintah. Karena mereka akan mengeluarkan bansos, dana PKH, dan lain-lain selalu dilakukan menjelang pencoblosan. Hal ini juga sesuai dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pada November 2023, hanya tiga bulan menjelang pencoblosan pemilu 2024, SMRC merilis bahwa 44 persen responden menganggap wajar dan bisa menerima money politics. Angka 44 persen itu tak begitu jauh dengan angka 32,99 persen. Asumsinya, kelas menengah yang sedikit di atas batas bawah masih menilai mencukupi nilai money politics.
Jika asumsi bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia sejatinya adalah sekitar 92,57 juta jiwa, maka mereka adalah pasar yang besar bagi tumbuhnya kerajaan penghisapan orang kaya terhadap orang miskin. Situasi inilah yang bisa melahirkan lingkaran setan kekacauan di negara yang dihuni oleh banyak orang miskin. Kemiskinan bisa melahirkan penguasa iblis berwajah malaikat. Bagi wilayah-wilayah – provinsi, kabupaten, kota -- dengan jumlah orang miskinnya besar sangat berpotensi melahirkan pemimpin-pemimpin buruk.
Kleptokrasi, Roving Bandit, dan State Capture
Dalam sosiologi ada satu teori yang dikenalkan oleh Emile Durkheim. Sosiolog dari Prancis ini mengemukakan bahwa dalam perubahan sosial ketika norma lama runtuh namun norma baru belum terbentuk maka akan terjadi anomali. Hal ini mendorong terjadinya deviasi sosial. Masyarakat mengalami kebingungan, kehilangan orientasi, dan tanpa pegangan yang solid. Tentang hal ini, ada satu kutipan menarik dari Antonio Gramsci: “The old world is dying, and the new world struggles to be born: now is the time of monsters.” Menurut cendekiawan Italia ini, dalam transisi besar, ketika sistem lama runtuh dan yang baru belum mapan, muncullah tokoh-tokoh kerdil secara moral dan intelektual, yakni para monster.
Situasi ini, sejak keruntuhan Orde Baru dan memasuki reformasi, Indonesia sedang menjalani transisi besar yang kini belum jelas wujudnya. Jargon membasmi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menumbangkan Orde Baru justru melahirkan KKN yang jauh lebih besar dan merata. Boleh dikata pada aspek ini reformasi telah gagal total, kecuali tumbuhnya demokrasi. Di daerah-daerah, masuknya reformasi juga berarti lemahnya kendali pusat. Sejumlah daerah otonomi baru lahir, misalnya, pada tahun 2000, hanya dua tahun setelah Orde Baru tumbang, lahir provinsi Gorontalo. Wilayah kecil yang secara sejarah, budaya, dan aspek sosial berbeda dengan Minahasa ini memisahkan diri dan membentuk provinsi tersendiri. Dengan demikian, di Gorontalo terjadi transisi dobel: mengikuti transisi pusat, dan terjadi transisi lokal. Situasi ini juga terjadi di sejumlah daerah dan provinsi lain yang mengalami pemekaran.
Dalam ilmu politik ada teori kleptokrasi, roving bandit, dan state capture. Tiga konsep politik ini cukup sesuai untuk melihat kondisi di Indonesia dan di beberapa daerah di Indonesia. Kleptokrasi berasal dari dua kata, klepto dan krasi. Klepto berarti mencuri, krasi adalah kekuasaan atau pemerintahan. Maksudnya adalah pemegang kekuasaan memperkaya diri, kroni, dan kelompok kecilnya secara sistematis dengan menyalahgunakan kekuasaan dan memanipulasi institusi. Teori ini di antaranya dikemukakan oleh Stanislav Andreski (pencetus awal, pada 1968), Jean-Francois Bayart, Susan Rose-Ackerman, Robert Klitgaard, Chistopher Hope dan Nicholas Shaxson.
Sedangkan teori roving bandit dikemukakan oleh Mancur Olson. Dalam buku Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorship (2000), Olson membedakan dua jenis bandit. Pertama, Bandit Bergerak (Roving Bandit): mereka menjarah suatu wilayah, mengambil semua yang bisa diambil, lalu pergi. Tidak ada insentif untuk membangun atau menjaga stabilitas. Mereka seperti perampok keliling. Mengambil sumberdaya lalu pergi. Kedua, Bandit Menetap (Stationary Bandit): mereka menyadari bahwa dengan menguasai suatu wilayah secara tetap, memungut pajak secara berkelanjutan, dan memberikan sedikit jaminan keamanan serta stabilitas ekonomi, mereka bisa mendapatkan hasil lebih besar dalam jangka panjang. Pada intinya, dengan dua jenis bandit itu, Olson hendak mengatakan bahwa kekuasaan (negara) tidak lahir melalui kontrak sosial, tapi melalui cara paksa dengan monopoli ‘kekerasan’ untuk melindungi mafia. Jadi sifatnya eksploitatif semata. Pengendalinya adalah interest group (untuk keuntungan kelompok kecil) dan motif rent seeking (korupsi, monopoli, izin diskriminatif). Para bandit mengendalikan penguasa.
Adapun konsep state capture berkembang pada akhir dekade 1990an dan awal 2000an oleh para peneliti Bank Dunia dan Bank Eropa (EBRD). Teori ini menjelaskan bahwa penguasaan proses pengambilan keputusan negara oleh aktor swasta untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Perumus utamanya adalah Joel Hellman, Geraint Jones, dan Daniel Kaufmann. Hal ini ditulis dalam buku Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies (2000). State Capture terjadi melalui suatu proses ilegal maupun tidak transparan oleh suatu kelompok tertentu dalam rupa kebijakan, undang-undang, atau aturan. Apakah proses pembuatan UU Cipta Kerja, UU Minerba, proyek infrastruktur strategis, dan UU BUMN yang melahirkan Danantara masuk kategori ini? Ini tantangan tersendiri bagi peneliti dan akademisi. State Capture berbeda dengan korupsi. Dalam korupsi, orang menyuap untuk menghindari aturan, sedangkan dalam state capture orang menyuap untuk mengubah aturan agar menguntungkan diri atau kelompoknya. Dalam state capture ada kontrol terhadap proses legislasi dan regulasi. Dengan demikian ada legalitas dan tentu hanya bisa dilakukan oligarki (persekutuan elite bisnis dan politik). Pelaku state capture ini tak patut disebut pencuri atau bandit, mereka sudah berkelas garong alias mbahnya maling.
Celakanya, tiga bentuk ini terjadi bersamaan di Indonesia. Di daerah memunculkan bandit yang menguasai kepala daerah, di pusat terjadi state capture. Adapun kleptokrasi merupakan fenomena merata di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah sejumlah orang yang diduga bandit sudah berhasil berkuasa, dan saat ini sedang berproses di Gorontalo.
Gramsci mengatakan, munculnya para monster tersebut – pencuri, bandit, dan garong – terjadi di masa transisi besar. Saat ini Indonesia sedang berada dalam fase transisi besar. Namun pertanyaannya adalah, apakah Indonesia bisa melampaui fase ini untuk menuju pada kemajuan dan kemakmuran? Yang sudah terang terjadi adalah monster itu berevolusi dari kelas pencuri, menjadi kelas bandit, dan kini sedang menuju kelas garong. Apakah mereka pada saatnya akan kenyang dan berhenti menjadi maling? Jawaban teoretisnya adalah hal itu bisa terjadi jika kita melakukan penguatan institusi, penegakan hukum, reformasi sistem politik, partisipasi publik di daerah, pemberdayaan dan penyadaran masyarakat, dan penguatan pers serta civil society. Semua elemen baik masyarakat harus bersatu. Tapi mulai dari mana? Pertanyaan inilah yang bikin frustrasi.
Gejala “kabur aja dulu” merupakan salah satu bentuk rasa frustrasi generasi muda. Dan jika ini semua dibiarkan maka Indonesia menuju pada tiga skenario – sesuatu yang sudah saya kemukakan sejak lebih dari 10 tahun lalu: menjadi negara budak, terpecah belah menjadi beberapa negara, dan memunculkan fenomena warlord (munculnya milisi bersenjata, preman-preman bersenjata, dan seterusnya). Tentu kita tidak ingin tiga skenario itu terjadi. Maka pilihannya adalah bangkit dan bersatu.

 2 months ago
27
2 months ago
27